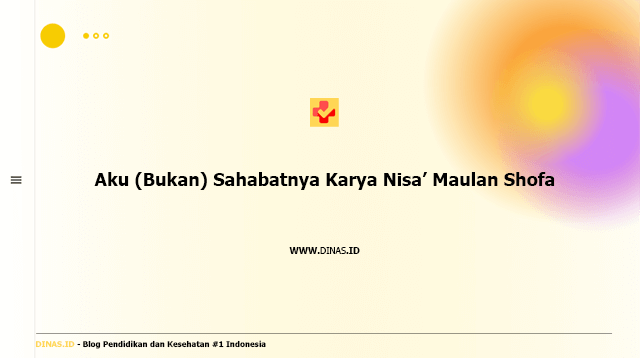Aku (Bukan) Sahabatnya
Oleh: Nisa’ Maulan Shofa
“Angeeee!” Aku berlari mengejar seseorang yang tengah berjalan terburu.
Lelaki itu menoleh. Menghentikan langkahnya untuk menungguku. Dengan beban berat yang dua kali lipat dari biasanya, aku tetap berlari menuju Ange. Alhasil, napasku naik turun tidak keruan.
“Dasar! Makanya jangan suka telat! Telat kok dipelihara!” ujar Ange sambil mengacak rambut lurusku yang tadi lupa kusisir karena terlalu gugup.
Aku hanya tersenyum menerima perlakuannya. Aku suka saat tangan kekarnya itu mengacak rambutku. Meskipun aku tahu, jika rambutku itu bisa berbicara, pasti ia akan memprotesku karena tidak memarahi tangan Ange.
“Kamu, Si Raja On Time, dan kau Ratu Ngaret. Kita memang cocok.”
Aku membenarkan posisi ransel gendutku. Hup! Hampir saja aku terjatuh akibat kehilangan keseimbangan, untung saja tangan Ange sigap membenarkan ranselku yang miring itu.
“Berat banget?” Ange mengerutkan dahinya. Alis tebalnya yang memang sudah menyatu menjadi semakin tak berjarak.
“Aku bawa banyak makanan untuk kita di bus dan di perkemahan nanti. Ah, aku semakin tak sabar untuk segera sampai di sana. Mendirikan tenda bersamamu,” ujarku dengan senyum yang semakin mengembang.
“Haha sudahlah, jangan kau terus berimajinasi seperti itu. Bus sudah menunggu kita. Jangan sampai kita diprotes 25 anak gara-gara acara imajinasimu itu. Ayo!”
Ange menggandeng lenganku. Aku hanya menurut lalu mengikuti langkah kakinya yang tegap. Aku sangat menyukai derap kakinya.
***
“Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang…” Aku memandu semua anggota camping untuk bernyanyi. Sangat gembira. Sangat bersemangat.
“Hei, sudahlah kamu duduk. Nggak bisa apa mulutmu itu dikunci sebentar saja? Telingaku bisa-bisa tuli karena suara rombengmu itu.” Ange meneriakiku.
Aku lantas diam merespon ucapannya. Memasang tampang segarang mungkin ke lelaki yang duduk tak jauh dari tempatku berdiri.
“Hei, ayolah! Aku hanya bercanda. Kenapa jadi garang seperti itu? Tak terlihat jujur jika aku menyebutmu Cinderella jika wajahmu jelek begitu.” Ange menarik tanganku. Membawaku duduk di sampingnya.
“Masih marah?” Ange bertanya dengan tatapan Ayolah-Jangan-Marah-nya.
Aku hanya memamerkan cengiranku selebar mungkin.
Seketika tawanya meledak dan membuat orang-orang di bus terlonjak sangking kagetnya.
Aku masih tetap diam.
“Beneran marahnya? Nggak nyesel ngambek ke aku?”
“Hei, bukannya tadi kamu yang bilang supaya diam sebentar dan tidak membuat telinga orang tuli? Aku mau tidur. Capek. Aku kan baru selesai konser dengan suara rombengku!” ujarku ketus lalu mencoba memejamkan mataku.
Semenit. Dua menit. Tiga menit. Hening.
Ange tak menggangguku lagi dengan pertanyaan Tak-Bisakah-Kau-Tak-Marah-Lagi-Kepadaku miliknya. Aku mulai kesal. Tidakkah dia mengerti aku tadi bercanda? Aku hanya ingin mendapat bujukannya!
Aku tak berniat untuk bertanya apakah dia percaya aku benar-benar marah atau tidak. Yang jelas, sekarang aku kesal. Kenapa dia tidak peka sedikitpun denganku? Seharusnya dia mengerti kenapa tadi aku bernyanyi-nyanyi tidak jelas. Hal itu karena aku terlalu bahagia akan terus bersamanya selama dua hari dua malam. Tidakkah dia mengerti kenapa aku (pura-pura) marah padanya? Itu karena aku ingin dia membujukku. Ayolah Ange… Kenapa kau begitu bodoh?
***
Sekitar pukul empat sore kami semua tiba di tempat camping. Sangat indah. Pepohonan rindang masih banyak berkeliling. Udaranya sangat sejuk. Dan tentu saja, tak ada polusi di mana-mana.
Pukul lima lebih seperempat, kami –para cewek– pergi ke sungai terdekat untuk mandi. Tentu saja setelah mendirikan tenda. Karena jika kami tak membantu mereka –para cowok– mendirikan tenda, maka kami terancam mati kedinginan.
Seperti yang kubayangkan, sungai di sini sangat indah. Bebatuannya seperti cips-cips cokelat di atas kue kering. Airnya mengalir tenang.
“Pelangi!” Tia, cewek berambut sebahu hitam dan berkulit putih mulus, berteriak. Semuanya terlihat takjub. Begitupun denganku.
Di kota, mana pernah kami melihat benda indah yang menggantung setengah dan berwarna-warni seperti yang tampak sekarang ini? Di sana hanya ada abu kehitaman yang terus menerus keluar dari corong pabrik. Membumbung tinggi dan mencemari lingkungan. Tak menarik sedikit pun. Di sana juga, hanya ada Pelangi yang merebut Ange dariku.
***
Acara api unggun telah dimulai sejak dua puluh menit yang lalu. Semuanya bergembira.
Kami memang sering melakukan perjalanan dan kegiatan seperti ini. Ber’tamasya’ meninggalkan kota hanya untuk mencari daerah sejuk yang bisa ditinggali meskipun itu hanya dua sampai tiga hari saja. Kami yang memang memiliki komitmen untuk menjaga alam, terus berkeliling mencari daerah yang masih ‘suci’ untuk sekadar ‘mencicipi’ kesejukannya.
“Hai,” ujar seseorang lalu duduk di sampingku.
Aku hanya menoleh sebentar lalu memberikan sedikit gumaman akan kehadirannya.
Tanpa kusangka, ia tertawa akan sikapku itu. Aku menoleh ke arahnya kembali, menautkan alisku dan memberinya tatapan sebal.
“Kamu cantik,” ujarnya dan membuat alisku rileks kembali.
“Oh seseorang, congkel saja mataku ini dengan parang bergerigi yang sangat tajam. Aku tak sanggup melihat mata berliannya. Dia sungguh cantik malam ini.” Ange berujar kembali dengan nada begitu ‘drama’. Dan aku tak suka ia berkata seperti itu.
“Tia! Kamu bantu aku, nggak? Aku butuh gunting, nih. Mulut cowok di sebelahku minta disobek-sobek!” teriakku pada Tia yang tengah menggelayutkan kepalanya pada pundak kokoh Ben, pacarnya.
Dia dan Ben hanya terbahak. Sementara yang lain tengah sibuk menghangatkan tangan mereka di depan api unggun.
“Kamu rela merobek mulutmu dengan tanganmu sendiri?” Ange bertanya tak percaya dan memberiku tatapan sangar.
“Bukan dengan tanganku, tapi dengan gunting yang diberikan Tia,” ujarku sambil memberinya senyuman tak ikhlas.
“Masih marah dengan tadi siang di bus? Aku cuma bercanda. Tahu, kan? Aku nggak sanggup kamu diemin gini. Apalagi senyummu jelek begitu. Ayolah, kamu itu punya senyum yang sangat indah dan wajib dibagi kepadaku.”
“Aku tahu senyumku indah,” ujarku sombong.
Dia terbahak lagi, mengacak rambutku yang telah kusisir dengan rapi.
“Aku mencintaimu,” ujarnya kemudian, lalu menarikku untuk menyandarkan kepala di pundaknya.
Aku hanya menurut dan mengguratkan senyuman. Tak menjawab dengan satu huruf pun.
“Coba Pelangi ada di sini,” ujarnya lagi.
Aku segera menegakkan kepalaku. Menatap Ange dengan kening berkerut. Dadaku bergemuruh tiba-tiba. Bagaimana bisa setelah ia mengatakan hal semanis ‘aku mencintaimu’, tapi sedetik kemudian ia mengandai kehadiran Pelangi?
“Kejam banget,” lirihku dengan perasaan tidak keruan. Mataku mulai berkaca.
“Kenapa? Dan dia juga pacarku. Pacar pertamaku,” balasnya dan semakin membuatku hancur.
“Tia!” teriakku dan langsung menyita perhatian semua anak-anak yang tengah bernyanyi tidak jelas di depan api unggun.
“Kenapa?” Tia merespon dengan sikap biasa saja. Wajahnya bahkan datar dan tidak menampakan ekspresi peduli.
“Aku serius nyuruh kamu ngambilin gunting. Bukan untuk merobek mulutnya lagi. Tapi membunuhnya. Dia sudah bosan hidup!”
Air mataku nyaris tumpah setelah mengatakan kalimat-kalimat itu ke Tia. Namun, di luar dugaanku, anak-anak malah kembali sibuk dengan lagu yang belum mereka selesaikan. Mereka seolah sudah paham dengan apa yang terjadi di antaraku dan lelaki di sampingku. Bahkan Tia pun melakukan hal yang sama.
“Aku bisa lompat ke jurang, asal kamu bahagia.” Ange mendekapku.
Aku hanya menghela napas. Mengenyahkan seluruh gemuruh yang muncul beberapa saat yang lalu. Aku masih tidak mengerti dengan sikap plin-plan Ange. Dalam sekejap, dia terlihat sangat manis dan membuatku lupa jika aku bukan satu-satunya. Namun, di detik berikutnya, dia tak mengizinkanku menyombongkan diri karena pada kenyataannya aku hanya yang kedua.
Dalam sekejap, di dalam dekapnya, aku berpikir bahwa aku tak layak mengucapkan “Selamat Tinggal”. Padahal, hanya dua kata itu yang bisa membebaskanku dari rasa bersalah karena telah menghianati perempuan cantik yang selalu kusebut sahabat. (****)
/// Cerita pendek atau cerpen ini adalah karya terbaik dari anak-anak KF (Kampus Fiksi).