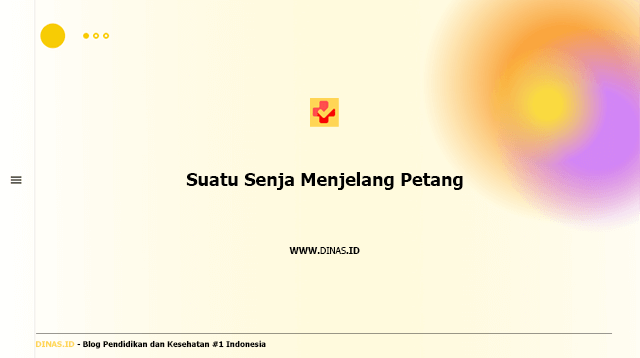Suatu Senja Menjelang Petang
Oleh: Ratna Pratiwi
Aku melangkah di sampingnya memikirkan kami, dia entah memikirkan apa. Aku berjalan di sisinya membayangkan esok, dia entah membayangkan apa. Aku merenungi hubungan kami, sementara ia entah tersenyum karena apa. Yang jelas tangan kami masih saling menggenggam, meski sadar tak lagi sejalan.
“Mau main apa lagi?” tanyanya masih dengan semangat yang sama.
Aku tak langsung menjawab. Masih sibuk menghitung langkah demi langkah menuju malam. Kulirik jam yang melingkar pada pergelangan tangan. Ah…berapa lama telah kami habiskan bersama? Dan dia masih menunda, entah karena apa.
Sendari tadi aku hanya memuaskan dirinya yang bersikeras mengelilingi taman bermain yang terkenal dengan icon boneka berhidung besar ini. Mencoba satu demi satu wahana yang dulu sering kami nikmati bersama sejak awal saling mengenal. Bahkan di sinilah kami memulai hubungan asmara ini. Aku ingat benar hari itu. Saat ia menyatakan cinta di atas bianglala ditemani kelap-kelip lampu kota yang tertangkap mata. Ah…memang terlalu banyak kenangan di sini.
“Aku lelah,” sahutku lirih memotong dirinya yang tengah bercerita—entah apa. Aku telah berhenti mendengarkannya sejak beberapa detik yang lalu.
Ia menghentikan langkah, kemudian menoleh pelan. Aku tak tahu bagaimana ekspresi yang ia tunjukkan saat ini. Karena sekali lagi aku masih sibuk dengan pikiranku sendiri dan sepenuhnya mengalihkan tatapanku pada sepasang flat shoes berwarna toska yang tengah kukenakan. Ya Tuhan…bahkan sepatu ini adalah sepatu yang kukenakan pada kencan pertama kami, di taman bermain ini.
Dapat kurasakan lesir napasnya yang mengalun pelan diiringi geraman rendah. Ia tahu maksudku. Aku bukan hanya lelah dalam artian fisik. Aku memang sudah benar-benar lelah dengan semua ini. Ia sudah terlalu lama menunda dan bermain. Dan aku terbawa bersamanya. Padahal bukan ini tujuan awal kami kemari.
“Kita cari tempat makan ya. Mau makan apa?” tawarnya masih dengan nada perhatian yang sama. Bahkan masih menyelipkan kasih dalam setiap untaian katanya yang mengalun lembut merasuki pendengaranku.
“Aku tidak lapar.” Lagi-lagi aku hanya bicara seperlunya. Hey, dimana diriku yang selalu cerewet setiap kami jalan bersama? Biasanya aku yang sibuk memilih wahana, biasanya aku yang rewel meminta makan, biasanya aku…biasanya aku yang memberinya perhatian. Dimana diriku yang dulu bisa menyahut setiap tanyanya dengan nada manja?
Kembali ia mendesah lelah. Kemudian ditariknya tanganku menuju sebuah bangku taman—tak jauh dari tempat kami berdiri. Tempat itu hanya diterangi cahaya remang dari lampu taman. Baguslah, semakin temaram akan semakin mudah bagiku menyembunyikan muram.
“Maafkan aku,” ucapnya memecah hening setelah beberapa saat kami hanya duduk terdiam.
Tidak, bukan maaf yang kutunggu meluncur dari bibir manisnya. Aku menunggu jalan keluar untuk hubungan kami yang kini setengah jalan. Tunggu. Setengah jalan? Jalanku atau jalannya?
“Aku tahu aku menjanjikan kejelasan atas hubungan yang semakin tak terarah ini. Kau tahu aku mencintaimu, kau tahu aku sangat berharap dengan hubungan kita, kau tahu bahwa bukan hanya dirimu yang menderita di sini,” ia memberi jeda, mengambil napas dalam-dalam seolah membicarakan perasaan adalah siksaan baginya. “Aku tak ingin berakhir.”
Kali ini aku menatapnya meski datar. Apa aku tak salah dengar? Ia tak ingin berakhir?
“Kau tahu kita tak punya jalan menuju akhir. Kau yang membuat semua ini terasa sulit,” ucapku sengit. Aku kesal, aku marah, aku sangat kecewa padanya. Tentu saja aku berhak merasa tersakiti di sini. Tentu saja aku berhak merasa dikhianati. Tidak. Ia bukan hanya mengkhianatiku, ia juga mengkhianati Tuhan kami.
Oh, baiklah. Aku tak ingin membahas ini tapi beginilah keadaanya. Aku dan dia berpacaran semenjak duduk di bangku SMA. Kami adalah pasangan yang bahagia. Berbagai mimpi telah kami rajut bersama. Kau tidak percaya? Tanyakan pada bangku-bangku merah bianglala, tempat kami merayakan hari jadi setiap tahunnya.
Semua baik-baik saja. Semua terasa begitu sempurna sampai dua tahun lalu ia memutuskan untuk lepas dari pelukan syahadat. Ia memutuskan untuk merubah imannya. Ia memutuskan untuk memberikan jurang diantara hunbungan kami yang sempurna. Bolehkah kukatakan ia adalah seorang bajingan?
“Aku benar-benar tak berdaya, sayang. Aku benar-benar tak tahu lagi harus bagaimana.”
“Kembalikan imanmu! Kembalilah ke jalan dimana dirimu seharusnya berada!” bentakku keras, tak lagi menghiraukan beberapa orang lewat yang memandang bingung ke arahku dan dirinya bergantian.
Aku kesal karena ketenangan yang ditunjukkannya. Kesal karena disaat aku begitu kalut karena hubungan kami yang dituntut berakhir oleh kedua orang tuaku, ia justru memasang wajah teduh yang membuatku muak. Dia bilang dia mencintaiku, lalu apa arti semua ini?
Berbeda denganku yang membentaknya penuh emosi. Ia merenung, kemudian tersenyum. “Bagaimana kalau jalan inilah jalan dimana seharusnya aku berada? Kau bicara tentang iman, apakah kau mengimani agamamu sekarang? Bagaimana jika jalanmu seharusnya bersamaku?”
Aku tercenung. Rasanya seperti ada aliran listrik mengejutkan syaraf-syaraf otakku mendengar kata-katanya barusan. “Kau mencoba mengajakku berpindah iman? Beraninya..” Aku ingin mengumpat namun kutunda saat ia menggeleng pelan.
“Tidak. Bukan seperti itu, sayang. Kau salah memahaminya,” ucapnya tenang. “Jika bicara tentang agama, berati membela apa yang kau imani. Jika bicara tentang apa yang kau imani, berati bicara tentang apa yang kau yakini. Apa yang kupilih sekarang bukan sekadar agama, bukan sekadar jalan, tapi iman yang telah menuntunku menuju kedamaian.”
Baiklah, aku mulai takut dengan kata-katanya. Dimana dia yang dulu selalu mengingatkanku tentang kewajiban lima waktu? Dimana dia yang dulu mendorongku belajar kitab suci agamaku? Dimana dia yang…oh, tunggu, bahkan setelah mengubah imannya, ia masih mengingatkanku untuk kewajiban-kewajiban itu. Dia masih kekasihku yang dulu. Masih dirinya yang penuh kasih dan penyayang. Masih dirinya yang setia pada satu cinta. Tapi berada di jalan yang berbeda.
Kurasakan air mata lolos begitu saja tanpa sanggup kucegah. Aku bahkan tak terisak. Air mataku sudah habis sekian lamanya untuk menangisi hubungan kami yang tak mungkin lagi diteruskan.
Diusapnya pipiku perlahan, sangat pelan hingga angin kalah halusnya dengan sentuhannya. Aku tak menangis. Setidaknya tidak di mataku. Tangisan yang ada jauh di dalam dada entah sudah sederas apa sekarang. Hingga tanpa sadar kian lama kian terasa menyesakkan.
“Kau ingin berakhir?” tanyanya masih dengan keteduhan yang sama.
Tidak. Aku tidak ingin berakhir. Aku masih ingin bersamanya hingga akhir. Tapi apa daya? Kisah kami tak lagi mungkin memiliki akhir selain harus benar-benar diakhiri.
Kami masih saling terdiam. Membiarkan napas bercinta dengan angin malam. Mengabaikan lalu lalang orang-orang yang sepertinya mulai beranjak pulang.
“Hari sudah semakn gelap. Kita naik bianglala satu kali ya sebelum pulang?” ucapnya setelah lama menunggu, kemudian menarik tanganku pelan.
Dari jarak ini, dapat kulihat sebuah benda yang telah menjadi wahana wajib setiap taman bermain itu berdiri dengan tegaknya. Seperti yang kukatakan tadi. Di tempat itulah kami selalu merayakan hari jadi kami. Hari ini seharusnya menjadi tahun ketujuh.
Kekasihku yang amat kucintai ini masih menggenggamku, meski tak terlalu erat—tidak seperti biasa. Seolah memang akan membiarkan jika tiba-tiba aku berniat melepaskan. Ia berjalan sekitar satu atau dua langkah mendahuluiku, membuatku tak bisa menangkap ekspresinya saat ini.
Kami mengantre. Jam-jam seperti ini memang banyak pasangan kekasih yang ingin menaiki bianglala berdua. Tinggal dua pasangan lagi, dan giliran kami akan segera tiba.
Tiba-tiba semua ingatan kami membayang dalam memoriku. Pertama kami berkenalan saat study tour, saat ia menyatakan cintanya, kencan pertama kami sebagai sepasang kekasih, ulang tahunnya, ulang tahunku, tahun demi tahun yang kami rayakan di sini. Semua memori itu menghujani ingatanku dan berputar seperti video rusak yang berulang-ulang hingga kepalaku terasa pening. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menghancurkan kenangan manis itu dengan perpisahan.
Giliran kami tiba. Tanpa menoleh, ia menarik pelan tanganku untuk maju, kemudian masuk terlebih dahulu. Saat itulah, kulepaskan tanganku dari genggamannya.
Bisa kurasakan tatapan bingungnya melihatku yang kini sepenuhnya menangis. Aku tak tahan. Aku tak kuat. Ternyata aku tetap tak bisa menghindari air mata ketika perpisahan telah menghadang.
Petugas yang menjaga nampak geram, namun mengurungkan niat untuk menegur ketika mendapati ekspresiku yang merana. Ia memilih untuk menenangkan antrean yang mulai menggumam.
Kami berbicara lewat mata. Aku menggeleng pelan sementara ia memandangku terluka. Kenyataannya momen seperti ini akan tetap datang, semua hanya tentang waktu. Dan yang kulakukan hanya mempercepat prosesnya.
Kemudian seolah mengerti, ia tersenyum sebelum akhirnya menutup pintu menuju tempatnya duduk. Membiarkan petugas kembali memutar bianglala dan meninggalkanku di bawah. Dan meski mendapati tatapan mencibir dari orang-orang yang menunggu di belakangku, aku tetap mundur dan pergi.
Dengan tidak mengikutinya untuk naik, kuharap ia mengerti bahwa aku memilih tinggal pada jalanku kini. Dengan melepaskan genggamannya, kuharap ia mengerti bahwa semua ini sudah harus diakhiri. Dan dengan air mata yang tanpa sengaja kutunjukkan padanya, kuharap ia tahu, bahwa perpisahan ini tak pernah mudah untukku.
Aku melangkah pelan menuju lapangan parkir. Sengaja kami datang secara terpisah, bukan karena merencanakan perpisahan, tapi lebih karena kepraktisan.
Sesampainya di dalam mobil, kurasakan ponselku bergetar. Ternyata ia yang mengirimkan pesan. Sebuah pesan yang semakin membuatku merasa sesak :
Kau tahu bahwa Tuhan telah berbesar hati mempertemukan kita, kemudian menghadirkan cinta untukmu dan aku.
Kau tahu cinta telah membesarkan kita, menjadikan aku bagian darimu begitu pula sebaliknya.
Karena cinta adalah milik Tuhan, maka izinkan aku tetap mencintaimu atas kuasaNya.
Kau tahu bahwa bagiku melepaskanmu takkan pernah mudah, maka terimakasih telah rela melepaskanku meski terluka.
Setidaknya kau dan aku tahu, kita berpisah bukan karena ingin.
Tapi karena memang Tuhan punya rencana lain.
Dalam lindungan kasih,
Yours.
Aku masih menangis. Namun seulas senyum menghiasi bibir. Aku tak tahu kapan akan siap memandang mata teduh itu nanti, aku tak lagi peduli hujatan orang yang mengatainya kafir, aku tak lagi peduli. Bagiku ia tetaplah dirinya yang selalu mencintaiku tanpa pamrih. Dan seperti yang telah kukatakan tadi. Perpisahan adalah sesuatu yang pasti. Yang kami lakukan hanya mempercepat proses perpisahan terjadi. Di sinilah kami memulai, dan di sinilah kami mengakhiri semuanya. Seperti yang telah ia katakan, kami berpisah bukan karena ingin, tapi karena Tuhan punya rencana lain.
**END**
Sebuah cerpen karya Ratna Pratiwi. Meski belum cukup bagus untuk menjadi juara di tantangan menulis #FiksiBianglala, mimin suka cerpen ini. Narasinya lembut dan penulisnya memasukkan pesan yang apik dalam tulisan ini. Beberapa typo yang masih nampak–yang akhirnya membuat cerpen ini kalah mentereng–adalah: diantara, terimakasih, sendari, icon (tidak dicetak miring), dll. Bila ada pembaca yang ingin memberi komentar pada cerpen ini, monggo.
Untuk Ratna, ayo lebih rapi dan teliti ketika menulis!
/// Cerita pendek atau cerpen ini adalah karya terbaik dari anak-anak KF (Kampus Fiksi).