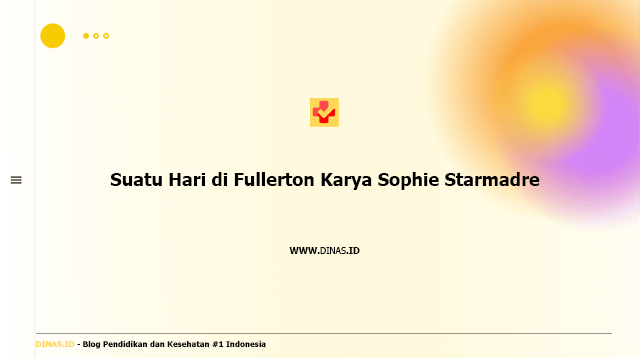Suatu Hari di Fullerton
Oleh: Sophie Starmadre
Sungai Singapura yang membelah kota membiaskan kemilau menakjubkan dari cahaya lampu kafe di sepanjang kawasan Clarke Quay malam ini. Meriahnya suasana di sekitar Merlion Park begitu kontras dengan perasaanku sekarang.
“Jadi ini yang kaumaksud dengan meeting?” Aku berbalik dari jendela hotel, memandang lurus-lurus ke matanya. Seluruh tubuhku berguncang menahan kecamuk perasaan yang menggelora di hati, namun aku berhasil mengucapkannya dengan nada datar, nyaris tanpa ekspresi.
Oh, seharusnya aku tak perlu semarah ini. Bukankah aku sudah tahu tentang mereka sejak dua bulan yang lalu? Lagipula aku sudah melakukan antisipasi, bukan? Aku mengerjapkan mata menahan perasaan nyeri. Melihat kenyataan secara langsung ternyata masih bisa memukulku walaupun aku sudah lama mempersiapkan diri untuk saat ini.
David, laki-laki yang terhitung dalam dua bulan ke depan akan mengikatku dalam sebentuk komitmen yang diakui secara sah oleh agama dan negara, menatap dengan sorot mata bersalah. Wajahnya pias sempurna.
“M-maafkan aku, Ra,” ujarnya lirih, nyaris tak kedengaran, “semua salahku. Aku menyesal,” sambungnya lagi. Kepalanya tertunduk dalam seiring bahunya yang terkulai lesu.
Dari balik tubuh tegap yang dulu selalu kukagumi itu, seseorang dengan wajah merah padam tengah berusaha menutupi tubuh polosnya dengan sehelai selimut di atas ranjang. Aku mendengus melihatnya, seolah itu mampu membendung luapan emosi yang tengah meletup-letup dari dasar hatiku.
“Tidak apa-apa, Darl. Sungguh.” Lagi-lagi aku berhasil memperdengarkan nada tenang yang sama. Kucoba menampilkan senyuman palsu berkelas layaknya milik Audrey Hepburn.
David menatapku tak percaya. “Kau tak marah, Sayang?”
Aku mendekat padanya lalu berkata, “Untuk apa? Kita berhak melakukan apa saja sebelum kita menikah,” sambungku sambil membelai pipinya. “bukan begitu, Sayang?”
Kutinggalkan David yang masih ternganga seperti orang bodoh. Dengan santai aku keluar sambil membanting pintu kamar hotel tersebut. Debumnya seolah meninggalkan gema kepiluan yang memantul-mantul di dinding hatiku yang kini purna retaknya.
***
“Jadi besok acara kita batal?” tanyaku, berlagak merajuk karena kecewa.
David mencolek ujung hidungku dengan jemarinya lantas tertawa. “Jangan begitu, Sayang. Kautahu bukan kalau meeting kali ini benar-benar penting dan tidak bisa ditunda lagi.”
“Tapi kau tidak akan macam-macam di Singapura, bukan?” Aku menatap matanya, mencoba mencari setitik kegelisahan di sana.
“Ya, ampun,” David menghentikan aktivitasnya lantas memeluk tubuhku dari belakang dengan erat, “kita sudah akan menikah dua bulan lagi, Ra. Tidak masuk akal kalau kau masih meragukan kesetiaanku,” bisiknya lembut, lantas menggigit pelan daun telingaku.
Aku hanya bisa diam. Hatiku terasa nyeri mendengar kebohongan-kebohongan yang mengalir lancar dari mulut manisnya.
“Lagipula aku pergi dengan Bowo. Tenang saja. Tidak ada perempuan lain di hatiku selain kau.”
Kali ini dia mengecup bibirku lama. Dalam hati aku menjerit. Bowo? Perempuan? Dasar munafik!
***
“Fullerton? Hmm…sudah dipastikan kamar nomor berapa? Jam berapa mereka check-in?”
Dengan perasaan tegang aku memilin-milin kabel telepon, menunggu suara itu menjawab satu per satu rentetan pertanyaanku.
“Baiklah, kalau begitu tolong booking kamar di bagian depannya, itu saja. Terima kasih.”
Aku menghela nafas panjang lantas mengalihkan pandang ke arah meja kerjaku. Semuanya sudah siap untuk besok. Paspor, tiket, dan kamar hotel. Tinggal satu hal lagi agar persiapanku baru bisa dikatakan seratus persen.
Aku meraih gagang telepon lagi dan menekan sejumlah nomor.
***
Dengan perasaan gentar aku memandang ke arah amplop coklat tebal yang sekarang tergolek di atas sofa itu. Penjaga apartemen menyerahkannya begitu aku pulang dari kantor tadi. Jantungku berdetak kencang ketika membaca nama pengirimnya. Bermodal kenekatan dan rasa takut kehilangan, aku memberanikan diri menyewa jasa detektif swasta yang pernah digunakan sahabatku untuk memata-matai mantan suaminya dulu.
Dan sekarang, ketika saatnya tiba untuk membuka amplop itu, mendadak sekujur tubuhku terasa dingin. Aku merasa lumpuh seolah tulang-tulangku telah diloloskan dan hanya menyisakan seonggok daging tak berguna. Inilah kali pertama aku bergelut dalam dilema terbesar yang pernah kuhadapi seumur hidupku.
Buka. Tidak. Buka. Tidak. Buka.
Perang batinku tidak juga berakhir ketika akhirnya aku memutuskan untuk membuka amplop itu dengan cepat, mencoba menutup rapat-rapat jendela hatiku dari suara-suara tak berkesudahan itu.
Dan terseraklah foto-foto itu. Saksi bisu kemesraan calon suamiku dengan kekasih gelapnya. Aku hanya bisa mengamati beberapa saja karena sudah tak sanggup lagi melihat sisanya. Toh tidak ada bedanya bagiku.
Menjijikkan!
Aku berlari ke kamar mandi, memuntahkan isi perut yang sedari tadi berontak minta dikeluarkan. Setelahnya aku benar-benar merasa lemas tak bertenaga. Rasa mual itu sudah merobek-robek isi perutku, sama halnya seperti yang dilakukan David pada hatiku.
***
Di mana lagi letak kesempurnaan kalau bukan pada ketidaksempurnaan itu sendiri?
David memang sempurna, terlalu sempurna malah. Seharusnya aku tahu kalau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Namun tak urung lututku gemetaran ketika siang itu, hanya delapan bulan setelah pertunangan kami, aku mendapati sebuah pesan singkat bernada mesra di ponselnya.
Siapa perempuan itu? Hatiku bertanya-tanya gelisah, mengingat tidak ada seorangpun lagi yang berani mendekati David-ku semenjak kami resmi bertunangan.
“Selidiki saja, Ra. Kau berhak melakukannya karena dia calon suamimu. Jangan sampai menyesal karena pernikahan bukan ajang uji coba.”
Itu saran Ina, sahabat karibku yang sudah mengalami perceraian pahit akibat diselingkuhi sebelum menikah kembali untuk yang kedua kalinya dengan seorang pria berkewarganegaraan asing.
“Tapi bagaimana kalau aku ketahuan dan David ternyata tidak berselingkuh? Rencana pernikahan kami bisa batal!” ujarku ragu. Angin kegelisahan sekarang bertiup kencang di hatiku, membisikkan sejuta kemungkinan yang bisa terjadi kalau aku tak segera mengambil keputusan.
“Take it or leave it,” Ina menghembuskan sekepul asap rokok dari bibirnya yang merah mengkilap. “Kalau kau tak sanggup, kau bisa memilih untuk melupakan pesan itu, Ra. Resikonya, kau mungkin akan dihantui tanda tanya besar,” dia berhenti sejenak sambil menatapku lekat-lekat, “seumur hidupmu,” sambungnya dingin, menunjukku dengan dua jari yang masih menjepit batang rokok.
Aku menggigil menyadari kebenaran kata-kata Ina.
***
Cantik, pujiku dalam hati, sedikit tersipu karena melontarkannya untuk diriku sendiri. Aku tersenyum bahagia menatap bayangan diriku yang memantul dari kaca besar di kamar. Pesta pertunangan baru saja selesai. Aku dan David memang sudah merencanakan semuanya dengan sempurna, termasuk rencana pernikahan yang kami impikan setahun lagi. Dan dengan cincin di jari manis ini, setidaknya akan membuat pikiranku lebih tenang. Kepopuleran David di kalangan perempuan, tak pelak memercikkan rasa khawatir di hatiku. Keindahan fisik dan wajah yang dibingkai dengan karakter yang tegas dan kuat, ditambah status sebagai satu-satunya pewaris perusahaan ekspor impor besar milik sang ayah, membuat David menjelma sebagai salah satu bujangan yang paling diinginkan. Aku yakin, berita pertunangan kami mampu membuat banyak perempuan tidak hanya gigit jari namun juga frustrasi menjurus ke depresi.
“Sepertinya aku benar-benar beruntung bisa mendapatkanmu,” desahku padanya suatu kali.
David menggeleng sebelum kemudian menggenggam salah satu tanganku dan mengecupnya pelan. “Akulah yang beruntung karena mendapatkan malaikat seindah dirimu.” Dia menatapku penuh perasaan, jenis tatapan yang sanggup membuat tubuhku bertransformasi menjadi agar-agar, lunak dan tak bertenaga. “Kau,” dia meletakkan telunjuknya di dadaku, “bertahta di hatiku selamanya,” katanya lagi, nadanya terdengar lembut mengalun di telingaku.
Perasaanku melesat terbang, bukan lagi menuju awan melainkan langsung ke Galaksi Bima Sakti. Aku menyimpan kata-katanya hari itu pada kotak harta di palung hatiku yang paling dalam. Dan dengan keyakinan penuh, aku menjalani hidup dan menyongsong hari pernikahan kami. Tidak ada perempuan lain yang lebih bahagia dariku. Aku yakin sekali.
***
Aku membiarkan pria tampan di hadapanku menghunjamkan bibir dalam-dalam ke milikku, sebelum kemudian menatap sinis ke arah dua orang yang belum lama berselang berdiri di depan pintu kamar hotel sambil menatap kami berdua penuh kengerian.
“S-siapa dia, Ra?” Suara David gemetar ketika mengucapkannya.
“Dia pacarku sejak setengah tahun yang lalu, Dave. Maaf, kalau aku sudah bermain api. Tapi, aku sungguh tidak tertarik punya suami abnormal sepertimu,” ujarku sambil melempar pandangan jijik pada David dan kekasihnya, “jadi, anggap saja kita impas. Permisi.”
Pada titik tertentu, balas dendam nyaris tiada bedanya dengan anggur: manis dan memabukkan. Masih dengan perasaan terluka namun puas, aku menggamit lengan kukuh si pria bayaran yang entah siapa nama belakangnya itu. Berlalu meninggalkan David dan juga kekasihnya, Bowo.
***
/// Cerita pendek atau cerpen ini adalah karya terbaik dari anak-anak KF (Kampus Fiksi).