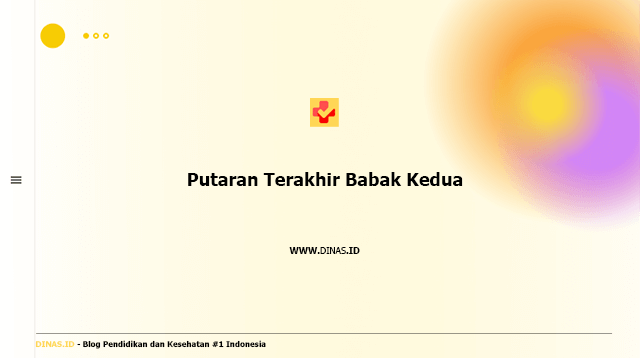Alun-alun utara Jogja basah sore ini. Hujan sudah berhenti, tetapi matahari masih meringkuk pasrah di balik mendung. Mungkin ia sedang menggerutu karena tidak bisa pamer senja pada orang-orang. Aku mendengus memikirkannya.
Kurapatkan sweater rajut tua yang membungkus longgar tubuhku. Tanganku terselamatkan dari udara dingin dengan kopi instan panas yang kubeli di minimarket terdekat. Terpaksa. Sesungguhnya aku lebih suka kopi tubruk tanpa gula.
Sesegera mungkin aku menuju konter bianglala, permainan favorit yang selalu kunaiki setiap sekaten digelar di kotaku. Oh, lihat, tidak ada antrean sama sekali. Yah, maklum saja. Memangnya siapa yang mau duduk dalam sangkar bianglala sehabis hujan? Sudah basah, dingin pula.
Setelah mendapat tiket, aku mendekat ke salah satu petugas bianglala. “Mas, mumpung sepi, boleh nggak saya naik sangkar yang….” Sepotong kalimatku belumlah usai ketika si petugas menoleh sempurna ke arahku, membuatku terkesiap. Dia menelan ludah, kemudian memaksakan sebuah senyum.
“Mau naik sangkar yang warna merah?”
Sudah satu jam kami duduk di trotoar tepi alun-alun sambil menikmati es krim. Maksudku, aku yang menikmati es krim. Es krim miliknya sudah habis bermenit-menit lalu. Setelahnya, dia tidak melakukan apa pun. Diam. Bisu. Matanya menatap ke kejauhan, ke area permainan sekaten.
“Ada apa?” tanyaku untuk ke sekian kali.
Dia tetap diam, malah menyelonjorkan kaki. Tangannya merogoh saku celana jeans bututnya untuk mengambil… rokok?
“Sejak kapan kamu merokok?”
Lagi-lagi dia tidak menjawab. Dengan gerakan kasual ia menyalakan korek untuk menyulut puntung rokok di mulutnya—seolah sudah terbiasa melakukannya. Aku mulai kesal dibuatnya. Seminggu tak ada kabar, inikah jawabannya? Kepulan asap rokok? Dengan medali perak OSN Biologi yang diraihnya beberapa bulan lalu, dia cukup pintar untuk tahu bahwa rokok tidak akan membawa manfaat bagi tubuhnya, kan? Kenapa dia mendadak tolol begini?
“Kalau kamu nggak juga mau menjelaskan alasanmu nggak masuk sekolah seminggu ini, aku pulang sekarang,” putusku. Hei, aku tidak main-main!
“Bapakku meninggal.”
“Hai,” sapanya.
Bianglala bergerak perlahan. Tanpa kuduga, Arya ikut masuk dalam sangkarku. Petugas lain tidak mencegahnya. Aku sendiri tidak tertarik untuk membalas sapaannya. Nanar mataku melihat penampilannya; rambut gondrong awut-awutan, bibir menghitam, kaos putih kelunturan, celana jeans dengan sobekan parah di lutut, dan sandal jepit yang solnya sudah menipis.
Dia tersenyum. “Kaget melihat keadaanku?”
Aku menjawab pertanyaannya dengan menyeruput kopi yang sudah setengah dingin. Otakku masih belum bekerja optimal. Inikah murid SMA pemegang beasiswa tiga tahun penuh dengan prestasi gemilang yang kukenal sepuluh tahun lalu?
“Beginilah aku, Nem. Kerja serabutan. Pagi sampai siang jadi office boy, siang sampai sore jadi penjaga konter buku, dan sebagai tambahan, selama sekaten tahun ini aku mencoba jadi tukang putar bianglala,” ceritanya diiringi tawa miris.
Lelucon buruk. Aku hanya mendengus. Sesaatmataku melihat ke arah lain, tidak sengaja menangkap pemandangan aneh; seekor burung nyasar membubung terlalu rendah, hampir menabrak puncak bianglala. Ketika fokusku kembali padanya,tatapannyaterlihat menerawang.
“Tiga bulan setelah aku di-DO, hidupku berubah kacau. Tekanan selama bertahun-tahun seakan meledak saat itu juga. Keluargaku sudah lama berantakan, dan saat-saat itulah aku menemui puncaknya. Tumpukan utang bapak dan ibukku, akulah yang harus membayarnya. Kukeluarkan seluruh tabungan untuk itu. Aku frustasi. Merokok, mabuk-mabukan… astaga, aku tak jauh beda dengan kedua orang tuaku ketika itu.”
“Saat aku sadar akan kekeliruanku, ujian akhir sudah berlalu. Terlambat. Aku sudah kehilangan kesempatan untuk lulus SMA. Dan seakan belum cukup, masih ada kabar yang membuatku semakin putus asa.”
Aku sudah kehilangan minat untuk menghabiskan es krim. Kami duduk berhadapan dalam sangkarmerah bianglala sekarang. Arya cukup sopan untuk tidak lagi mengepulkan asap ke mukaku. Ia membuang puntung rokoknya ketika kami naik.
“Sekolah sudah tahu apa saja yang kulakukan seminggu ini. Aku tahu mereka kecewa dengan perbuatanku; ikut tawuran, minum, merokok. Tinggal menunggu waktu hingga aku dikeluarkan dari sekolah.”
Aku melotot mendengar pengakuannya. Dia ini tolol atau bagaimana, sih? Lupakah dia bahwa ujian akhir tinggal sebulan ke depan?
“Setelah ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Mungkin ini putaran bianglala terakhir kita, Nemea.”
Kudengarkan setiap ucapannya tanpa menyela. Aku begitu takjub melihatnya berbicara ekspresif—persis seperti dahulu kala, ketika semua masih baik-baik saja. Tanpa terencana, aku terjebak kembali dalam kenangan lama; masa-masa SMA yang begitu indah menyilaukan.
“Aku menghamili anak orang. Tentu saja aku menikahinya. Untung dia perempuan baik-baik. Sial baginya, karena terjebak rayuan bodohku. Seharusnya dia mendapat suami yang lebih baik. Tapi ternyata, keluarga kecil kami cukup bisa berbahagia walau harus hidup pas-pasan.”
Dia tertawa, sementara kenangan masa lalu yang sempat terputar dalam benakku pudar seketika. Rahangku mengeras. Mulutku menipis. Udara terasa menyesakkan untukku bernapas.
“Nemea, kamu kenapa?”
Ketika akhirnya oksigen berhasil memasuki rongga dada, tersengal aku mengeluarkan suara, “Bukankah dulu kamu bilang kita tidak perlu bertemu lagi—bahwa saat itu adalah putaran bianglala terakhir kita, Arya?”
Aku sudah tidak sanggup berbicara. Tenggorokanku tercekat. Gemetar aku melihat kedalaman tatapannya; keruh, gelap, kelam. Tidak ada lagi binar semangat terpancar dari kedua matanya.
“Seminggu yang lalu, bapakku meninggal karena overdosis miras oplosan. Tiga hari setelahnya, ibuku yang dulunya wanita panggilan kabur bersama laki-laki lain. Orang tuamu tidak akan membiarkan anak gadisnya berteman dengan laki-laki berlatar belakang keluarga sepertiku, kan?”
Putaran bianglala terhenti. Bergerak turun, berhenti lagi. Begitu berulang-ulang. Petugas mengeluarkan penumpang dari sangkar satu per satu. Akhirnya, tibalah saatnya kami harus turut meninggalkan sangkar.
“Nah, putaran bianglala kita sudah berakhir, Nemea. Kita harus turun sekarang.”
Dan dia pun melompat keluar dari sangkar, melangkah lebar-lebar, tanpa menengok ke belakang. Sementara itu, aku duduk termenung memperhatikan sosoknya yang kian menjauh, menikmati lesir lembut angin ditingkahi suara petugas bianglala yang tidak sabaran menyuruhku turun.
Arya terperangah.
“Astaga, Nemea, peristiwa itu sudah sepuluh tahun yang lalu. Usia kita baru belasan tahun ketika itu. Tidak bisakah kamu menganggapnya sebagai kenangan indah semasa SMA?”
Dengan segera dia menerima tatapan tajamku.
“Usiaku 28 sekarang. Belum menikah. Sejak hari itu, belum pernah aku dikecewakan laki-laki lain, karena aku memang menolak jatuh cinta. Setiap tahun aku datang ke sekaten hanya untuk naik bianglala. Tidakkah kamu paham, Arya?”
Hening.
Arya mengerjap dua kali.
Kopiku sudah dingin sepenuhnya.
/// Cerita pendek atau cerpen ini adalah karya terbaik dari anak-anak KF (Kampus Fiksi) – No Name