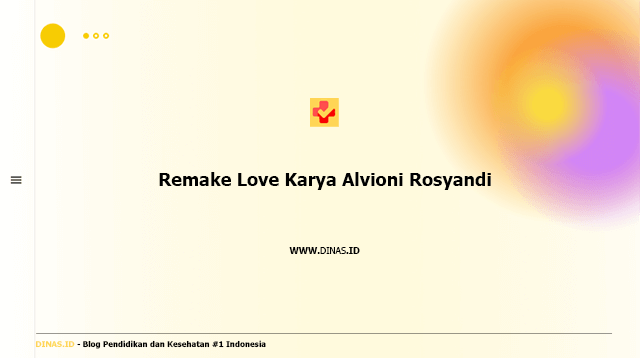Remake Love
Oleh: Alvioni Rosyandi
“Menurutmu apa yang berbeda dalam hidup ini?” tanya Dian dengan suara beratnya yang terhalang onggokan batu es yang digerataknya sejak tadi.
“Sekarang yang berbeda itu, aku,” jawabku datar. Aku hirup kuah bakso yang asapnya bergulung sejak tadi di depanku.
“Serius Ta,” tanyanya menuntut. Dia tak lebih seperti wartawan kampus yang setiap hari mondar mandir di sekitarku. Aku seperti selebriti dengan skandal hidup teramat rumit. Membingungkan.
“Gue serius…”
Dian mengehela napas. Es teh manis di depannya sudah surut. Diseruputnya habis sejak pertama duduk. Laki-laki berparas cantik itu temanku sejak SMA. Kami kembali bertemu di Universitas dengan jurusan yang berbeda. Bukannya kampus Dian nggak punya kantin atau dia nggak punya teman, tapi katanya mengobrol denganku itu hal menenangkan yang ada di kampus.
Di mata Dian, kampus itu gedung berhantu. Mencekam. Menakutkan. Berbau darah. Amis. Waktu-waktu bahkan berjalan lamban, seperti malam yang tak kunjung menemui pagi. Dian tersiksa lantaran jurusan hukum yang menjeratnya tiga tahun belakangan. Menjadi petinggi negara yang menegakkan hukum, itulah impian orang tuanya. Penting? Tidak bagi Dian.
“Ta, serius deh, gue tau lo yang dulu dan sekarang itu udah beda lantaran cowo aneh nggak jelas yang…” ucapan Dian menggantung ketika mata bulatku menatapnya tajam. Melemparkan sayatan-sayatan tipis yang menyakitkan. Sakit. Pedih. Bibirnya terkatup. Matanya yang membalas tatapanku meneriaki pertolongan dan ucapan maaf yang lebih keras dari teriakan TOA di Masjid depan.
“Sorry…” nyatanya, suara besar Dian cuma mampu keluar beberapa oktaf saja. Terdengar lirih terbawa angin. Menyesal.
“Udahlah, santai aja,” wajahku yang tak berubah manis masih menjanggal pikirannya. Pasti.
Ketika siapa saja mengungkit masalah itu, aku menjadi sensitif. Masa lalu. Sudah jelas dia masa lalu, kenapa aku masih peduli? Itulah sebenarnya yang membuatku jadi sensitif. Aku terusik bukan karena dia, tapi karena diriku sendiri.
Aku risih. Kesal. Tidak suka. Marah. Sedih juga. Tapi, batinku tidak mau mengakui perasaan tidak enak itu. Menyakitkan. Menyebalkan. Dia akan makin besar kepala kalau tahu aku masih memikirkannya.
“Oke! Kita ganti topik..” dia ajukan usulan yang membuatku tidak enak hati.
Lagi-lagi aku membuat Dian tidak nyaman. Padahal dia jauh-jauh datang ke gedung Seni dari gedung Hukum yang jaraknya melewati empat buah gedung jurusan lain, kemudian menyeberang ke parkiran yang luasnya lebih besar dari stadion dekat GSG. Capek? Pasti. Walaupun dia selalu menunggangi motor matix yang dia beli dari hasil manggung di kafe-kafe. Tetap saja perjuangannya boleh diacungkan jempol. Hebat. Tegar.
“Lo mau seminar kapan? Boleh gue dateng?” tanyaku dengan pertanyaan paling tidak menyenangkan. Setidaknya bagi Dian.
Wajahnya berubah malas. Dia gantian bad mood.
Hujan yang tak kunjung reda diluar bersahut-sahutan dengan gemuruh hati kami masing-masing. Sudah tahu tidak nyaman, aku masih menanyakannya. Dan dia, sudah tahu aku tidak nyaman, dia malah sempat membahasnya.
Jadilah sekarang dunia kami bagai film horor. Dingin. Mencekam.
“Bulan depan. Maunya bokap,” ujarnya dengan nada dingin terkendali.
“Gila! Bukannya lo baru bimbingan sebulan? Apalagi ini baru semester keenam lo. Sekarang lo mau seminar dalam waktu dekat? Gokil!” seruku tak percaya.
Dian tergelak. Dia acak-acak poni yang menutupi dahi lebarku. “Makasi! Gue pikir gue juga gila! Atau malah bokap gue yang gila,” ujarnya asal ceplos.
“Hush! Nggak boleh gitu. Dia kan cuma mau Ardian Rivano tersayang KUMLOUT!” kataku menekankan kata-kata itu dengan mata berbinar. Suasana di antara kami mulai mencair. Dian tak pernah larut dalam kerumitan hidupnya terlalu lama. Itulah yang aku suka darinya. Tidak memusingkan apapun yang sebenarnya patut untuk dipusingkan.
“Pokoknya kalo gue seminar, lo harus dateng! Seminar gue nggak akan mulai kalo lo nggak ada disana!” ancamnya.
“Ish, maksa. Segitu ngefansnya lo sama gue, haha.”
Dian tidak menyahut. Dia diam, menatap mataku. Kami bertukar pandang.
Deg!
Lagi! Detakan aneh ini muncul dari jantungku. Setiap mata kami beradu pandang. Sunyi. Senyap. Membeku. Dingin. Kaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Duduk sembari memangku jantung yang sewaktu-waktu bisa menggelinding ke bawah karena terlalu semangat berdetak.
Tanganku masih membujur di atas meja. Di samping mangkok bakso yang masih dihuni tiga butir bakso dan beberapa helai mie kuning.
“Nita!” suara cempreng yang lebih rebek dari kaleng rombeng itu terdengar sudah. Cici, teman sekelasku yang centilnya gak pake woles.
Aku gelabakan. Panik. Mataku mencari-cari tumpuan yang tak pelak jatuh di mata milik Dian. Lagi dan lagi.
“Lo dicariin pak Anwar. Katanya lo lolos audisi dancer yang bakalan dikirim ke Italia itu loh,” ujar Cici bersemangat.
Italia? Aku? Benarkah?
Aku diam. Shock. Senang. Tapi, sedih. Aku lirik Dian yang menunduk. Aku tidak senang melihat wajahnya disembunyikan begitu. Kenapa?
“Ayo buruan!” Cici menarik tanganku. Menggeretku tanpa sempat bicara apapun lagi padanya. Pada Ardian.
***
“Serius lo Ta? Demi apa lo? Nggak usah ngayal lagi deh Ta!” mata sipit Cici yang menjadi identitas awal kalau dia keturunan Tionghoa itu dibesar-besarkan.
Senja yang aku peluk sore ini, kulepas sudah tatkala surat yang aku baca terlihat layu termakan waktu. Lama. Sejak kapan surat ini ada di sela-sela tanaman suplir di depan rumahku?
Tak puas, Cici meraih kertas itu, lalu membacanya cukup keras.
Hei Ta, pasti kamu kaget kalau baca surat dari aku ini. Jangan kaget dulu, masih ada kejutan lain yang bakalan bikin kamu lebih kaget lagi.
Kita kenal udah lama ya Ta, dari SMA. Kamu, aku, dan Dian. Bedanya, Dian nyata dan aku enggak. Tian dan Dian, menurut kamu apa bedanya dua orang itu dalam hidup ini?
Kalau kata Dian sih bedanya, Tian itu orang yang kamu suka dan Dian itu orang yang ribet banget dan ngerecokin waktu makan siang kamu. Bener ya?
Bertahun-tahun aku hidup dalam bayangan yang aku sendiri nggak tau kenapa nyiptain dunia yang kayagitu. Aku seperti nyata di mata kamu. Aku seperti ada dan bener-bener bisa bikin kamu tersenyum. Aku juga orang yang bisa buat kamu kembali semangat. Kata Dian, di mata kamu, aku itu satu-satunya orang yang bakalan berkata IYA saat seluruh dunia berkata TIDAK.
Begitu kan?
Maafin aku ya Ta. Aku udah kelewat batas buat deket sama kamu. Aku pikir caraku bener Ta. Ternyata, caraku salah. Aku yang seperti ini cuma bakal nyakitin kamu.
Jangan kaget dan jangan sedih kalau tiba-tiba aku nanti menghilang. Jaga diri kamu baik-baik ya Ta. Mulai sekarang cuma ada Dian. Lupain Tian. Kalopun kamu nggak bisa terima Dian, ya udah pokoknya jangan bocorin surat ini ke dia.
Dan Ta…
Kalau kamu ngelabrak Dian, aku anggap kamu baca surat ini dan marah.
Tapi, kalau kamu diam, kamu berarti belum baca atau kamu udah baca tapi emang nggak peduli sama aku. Itu jauh lebih baik.
“Gila! Nih orang siapa sih Ta?” sergah Cici.
Aku tetap diam. Memakan air mata yang aku tahan di hati yang terluka. Bingung. Siapa saja, tolong jelaskan ini.
Dian!
Aku raih jaket di dinding sofa. Beranjak pergi. Aku harus memuaskan hati yang terluka ini. Mencari kejelasan. Siapa Tian. Dimana dia. Kenapa dian nggak bilang apa-apa selama bertahun-tahun ini. Kenapa aku sendiri yang dibuat gila!
Kafe bernuansa Eropa klasik itu kudatangi lagi. Kali ini bukan untuk menikmati sajian musik Dian, melainkan untuk mengitrogasi laki-laki itu. Tian, laki-laki yang hidup bersama surat, telepon, dan sms selama aku SMA hingga awal perkuliahanku itu, siapa?
Melihat mataku yang memerah, petikan gitar Dian berhenti di kunci G. Kami bertukar pandang. Lagi. Gemuruh di hatiku mencuat ke permukaan. Mungkin saja pengunjung yang duduk di sekitarku mendengar riuh rusuh yang berasal dari hatiku.
“Besok gue seminar, awal untuk masa depan, itu kata bokap. Bertahun-tahun gue hidup dengan skenario mereka sampe-sampe gue iseng bikin skenario hidup gue sendiri. Gue bahkan melibatkan seorang gadis…” matanya jatuh ke mataku yang berkedut.
Napasku sesak. Tubuhku bagai melayang di udara. Pijakan ini licin. Aku terhuyung, tapi Cici menopang tubuhku cepat.
“Dan untuk dia gue bakalan nyanyiin lagu ini. Lagu ini cuma dua orang di dunia yang tahu, dia dan dia. Tapi sekarang gue jadi orang ketiga yang tau…”
Kau tersenyum, aku tidak tahu
Kau menangis, aku tak melihat
Tapi ada cinta yang tersimpan dalam
Di hatiku…
Di hatimu…
Menari dalam untaian senja
Kubalut dengan untaian nada
Melody indah yang kuciptakan, kuingin kau dengar
Untaian kata yang kuuraikan, mengertilah itu
Kau percaya aku ada…
Aku tahu kau ada…
Tapi dunia tak seindah yang kita inginkan
Dalam kehidupan nanti
Aku mau kau mengerti
Karena masih ada alasan untuk aku jatuh di hatimu lagi..
Tetesan dingin yang merembes di pipiku juga menghuni pipinya. Aku tidak tahu apa alasan dia meneteskan bulir-bulir kesakitan itu. Disini aku yang terluka, aku yang kecewa. Dia menipuku!
Teman? Sahabat? Terkutuklah kata-kata itu!
“Ta, lo kenapa?” tanya Cici cemas. Dia guncangkan tubuhku yang kaku menatap depan. Ke arah laki-laki bermuka dua. Mungkin.
Dia sakit? Dia gila? Dia membawaku masuk ke dalam dunia gilanya? Sinting!
Aku lari. Pergi. Menerjang hujan dan gemuruh hati yang makin besar. Kabut di jalanan kuterabas habis. Mata ini tak lagi jelas menangkap jalanan ramai di depan. Seharusnya aku mendengar suara Cici berteriak sambil mengejarku. Tapi tidak.
Langkahku terhenti. Aku tidak jelas melihat sudah sejauh mana aku berlari dari kenyataan ini. Aku takut. Aku sedih. Kecewa. Semuanya bagai diramu dalam wadah hati yang terluka.
Sinar yang bukan berasal dari matahari senja menuntunku ke pojokan jalan. Melipir. Beringsut minggir. Membawa tubuh yang kuyup ini untuk diguyuri darah segar. Pedih. Tapi ada yang lebih pedih dari itu. Luka akibat kebingungan yang kubiarkan berlarut-larut.
Kenyataan. Itu kebiasaanku. Aku takut menghadapi kenyataan hidupku. Aku takut mengklarifikasi apapun yang sebenarnya penting.
Aku kehilangan. Mungkin nyawaku yang sekarang aku hilangkan—
***
Mataku mengerjap. Terang benderang. Lampu neon putih itulah yang pertama tersenyum padaku. Dia menempel pada atap putih yang kaku. Dingin. Layaknya tanganku yang ditusuk jarum infus.
Aku. Pasti di rumah sakit. Batinku yakin. Aku kan kecelakaan, mungkin beberapa jam yang lalu atau malah…
“Akhirnya kamu bangun juga Ta, bunda kira bunda nggak bakalan ketemu kamu lagi sayang,” suara lembut wanita paruh baya ini seperti memendam kerinduan yang sudah sangat lama. Selama apa?
“Dua minggu kamu koma, Ta,” sambungnya sambil memeluk kepalaku yang diperban.
Aku merasakan nyeri. Di kepala. Punggung dan dekat perutku, sebelah kiri. Sepertinya ada jahitan disana.
“Bunda nggak tahu lagi kalo aja kamu nggak diselametin, mungkin bunda udah kehilangan kamu…” dia menangis. Wanita berwajah pucat ini menangis. Aku bingung kenapa bunda begitu mengkhawatirkan keadaanku. Aku kecelakaan biasa. Seingatku aku hanya terlempar dan keningku mencium trotoar. Lutut dan sikuku hanya terseret di aspal. Tidak ada yang lebih serius dari itu.
Beberapa detik kemudian siluet seseorang menyilat ke arahku. Dian. Laki-laki sinting itu!
Tapi, senyumnya sedetik kemudian hilang. Tertutupi truk kuning yang menyeretku ke pinggir.
Ah! Sakit! Kepalaku!
Aku menyentuhnya. Meremas selimut dengan tangan yang lain. Wanita muda berseragam putih kemudian datang menenangkanku. Tak lama itu aku berhasil ditenangkan. Nyeri di kepala ini hilang, meski tak sepenuhnya.
Mataku yang kesakitan dengan siluet aneh tadi, kini menangkap sosok teman dengan wajah tak menyenangkan.
“Cici…” suara parauku memanggil nama gadis yang sejak tadi berdiri di depan pintu. Matanya memerah. Bengkak. Tak biasa-biasanya Cici seperti itu. Dia kan gadis kuat. Bagaimana bisa dia menangisiku dua minggu berturut-turut sampai wajahnya membengkak begitu.
“Maafin gue Ta…” suara lirihnya terdengar pelan. Dia serahkan sebuah amplop yang tak cantik lagi. Isinya tentu saja surat yang tak muda lagi.
“Dari siapa? Laki-laki sinting itu?” tanyaku berdecak sebal.
Meski kepala diperban. Punggung kaku karena berbaring dua minggu. Belum lagi jahitan di perut masih basah. Aku tak henti-hentinya mengutuk laki-laki itu. Menyebalkan. Ah!
“Baca dulu Ta…” pinta Cici penuh permohonan. Wajahnya memelas. Di sampingku, bunda mengurut pelan pundak yang terasa kaku.
Apa yang sebernya kamu pikirin, nggak sama dengan fakta yang ada. Mungkin kamu marah kalau lagu ciptaan Tian itu aku nyanyiin. Aku berasumsi itu, Ta. Tapi, Cici detik itu juga melabrakku dan menyampaikan asumsimu yang konyol itu.
Sakit?
Aku nggak sakit Ta. Tian itu bukan aku, bukan seperti pikiran yang berkelibat sesaat dalam otakmu. Tian itu kembaranku. Dia itu ada tapi nggak nyata dalam hidup kamu. Dia selalu ada di sekitar kamu sampai dia pergi dan ngijinin aku buat ngelindungin kamu.
Jangan melulu salahin Tian, Ta. Aku yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Dia ngeliat foto waktu kita study tour di Lombok. Itu pertama kalinya aku lihat Tian tersenyum dan bangun dari kesakitannya. Dan aku senang karena ternyata kamu baik, mau nemenin Tian meskipun cuma lewat surat dan telepon.
Ngeliat semua itu, aku menyerah untuk ngedapetin kamu. Buat Tian, yang nggak ngerasain hidup normal dalam waktu lama, jatuh cinta sama kamu itu hal yang paling membahagiakan buat dia. Dan itu jadi hal paling baik yang bisa aku lakuin buat dia.
Surat yang dia selipkan di pot suplir rumahmu dua tahun lalu adalah surat terakhir yang mampu dia tulis sendiri.
Aku tahu, meskipun orang lain bilang kalau mustahil jatuh cinta dengan dunia maya. Tapi, kamu dan Tian ngebuktiin kalau cinta itu bisa dimulai kapan aja, dimana aja. Semua yang baik kalian serap, dan kalian mulai dengan cinta. Tapi, waktu nggak cukup baik. Tian nggak bisa selalu ada buat kamu.
Dan aku kira, aku bisa. Ternyata aku juga enggak.
Aku mencintaimu, Ta. Di kehidupan selanjutnya aku nggak akan kalah dengan Tian. Aku pasti buat kamu jatuh cinta sama aku dan aku akan buat skenario hidup yang lebih baik dari ini. Menyenangkan. Cuma kamu dan aku.
Wajar menurutku kalau aku dihujani air mata sekarang. pertanyaan bodoh yang lain masuk dalam benakku adalah, dimana Dian?
Pertanyaan yang jawabannya cuma buat aku menangis sejadi-jadinya.
Mungkin sulit buat kamu ngerasain cinta aku selama dua tahun belakangan ketika tanpa Tian. Karena itu, saat kamu membutuhkan sebuah hati, aku mendonorkan milikku. Ta, aku harap sekarang saat hati itu jadi milikmu, kamu bisa rasain cinta yang bertahun-tahun aku tanam dan aku rawat disana.
Itulah paragraf akhir dari surat Dian. Laki-laki sinting yang mencintaiku dengan cara yang konyol. Seharusnya kalau dia mencintaiku, dia jangan mau kalah dengan bayang-bayang Tian yang berkelibat dalam otakku. Dia juga seharusnya ungkapin itu sejak dua tahun lalu waktu Tian udah menghilang.
Kenapa? Kenapa baru sekarang?
“Aku tuh cinta sama kamu, Dian. Aku bukannya sulit ngerasain, aku cuma bingung, aku nggak tahu perasaan apa selama ini. Uh..uh…”
Pelukan Bunda menjadi balutan hangatku. Ini seperti mimpi. benarkah dia pergi? Dua-duanya? Tian dan Dian?
Uh…uh…
***
Aku memeluk bunga yang berbeda. Mawar putih dan bunga Matahari. Keduanya aku letakkan bersebelahan. Mawar putih untuk Tian dan bunga Matahari untuk Dian. Bagai mengusap dahinya yang selalu ditutupi rambut ikal kepirangan, aku mengusap nisan Dian.
Tidak. Aku tidak menangis. Aku sudah habiskan air mataku sebelum pergi kesini.
“Aku menunggu kamu kembali, saat itu aku janji, aku dan hati ini siap menampung cintamu yang teramat besar…” senyumku terkembang. Kutaburkan bunga lain yang aku jinjing tadi.
“Lain waktu semoga kita bisa ketemu, Tian…”
Aku melangkah pasti. Meninggalkan dua orang yang mencintaiku dengan teramat gigih. Cinta mereka besar. Aku yang masih belum siap merengkuhnya. Aku tidak merasa kehilangan mereka. Mereka selalu hidup. Terutama Dian.
“Kepergianku ke Italia bukan untuk menghindari kenyataan seperti kebiasaanku. Melainkan untuk menyongsong impianku,” ucapku pada wartawan kampus yang sebelumnya mewawancaraiku terkait pertukaran pelajar ke Italia.
/// Cerita pendek atau cerpen ini adalah karya terbaik dari anak-anak KF (Kampus Fiksi).