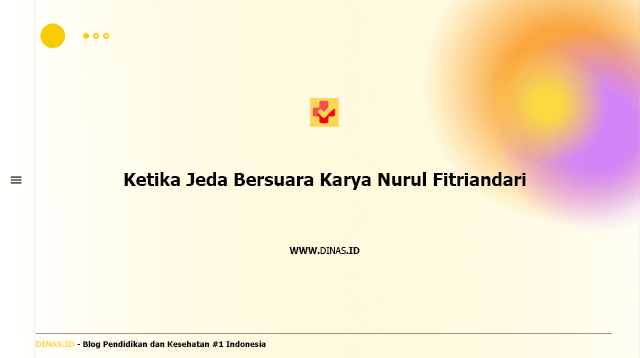Ketika Jeda Bersuara
Oleh: Nurul Fitriandari
Langit kian hitam. Barisan anak hujan masih tertumpah. Aku duduk termangu memandang ke luar jendela. Menerawang kosong, menatap jalananan basah yang tak bisa dikatakan sepi.
Beberapa orang sibuk mengembangkan payungnya. Beberapa orang lainnya, rela membasahi pakaiannya melawan deras air hujan. Berlari-lari kecil saat sebuah taksi dan mobil-mobil angkot kuning mulai datang menepi.
Dua puluh tiga jam lagi, aku membatin dalam. Gelisah menatap lampu arloji digital yang berkedip-kedip membentuk kumpulan angka. 9:45. Telapak tanganku berkeringat. Keringat dingin, atau ketakutan?
Kuedarkan pandangan ke penjuru ruangan. Gelap. Dan aku baru tersadar, banyak meja kerja yang sudah kosong dari penghuninya. Hanya tersisa segelintir karyawan yang berniat lembur hari ini. Tapi aku masih enggan beranjak dari tempat ini. Bayangan kecemasan itu mulai berdatangan. Saat deretan adegan tadi siang kembali menyapa, saat semua karyawan masih terkumpul lengkap di ruangan ini.
“Siapa? Bapak Azka?” tanya Dena, pegawai paling senior di perusahaan ini. Tapi bentuk wajahnya yang chubby sepertinya sukses menutupi jumlah puluhan tahun angka usianya.
Kuletakkan secangkir cappucino di meja Dena. Telingaku berusaha mencuri dengar apa yang dibicarakan. Maklum, posisiku yang hanya berstatuskan sebagai karyawan cleaning service di perusahaan ini membuatku sedikit tahu diri. Tidak berani ikut terlalu dalam, mengurusi hal-hal intern di perusahaan.
“Iya, kabarnya memang Pak Azka yang mau gantiin Pak Soberi,” balas Neta. “Denger-denger, sih, katanya lebih perfectionist dari Pak Soberi.”
“Ya iyalah, secara mereka bapak sama anak” sahut Reno, satu-satunya pejantan tangguh yang hobi ngerumpi ria di bagian administrasi ini. “Makasih, ya, Ra,” ucap Reno lagi, saat kuletakkan secangkir black coffe di atas meja kerjanya.
“Oh, buah jatuh memang nggak jauh dari pohonnya, ya?” tanya Neta memastikan. “Tapi, moga-moga nggak segalak Pak Soberi,” ucap Rena. Entah ditujukan pada siapa. Tapi nyatanya, Neta dan Reno sama-sama menjawab dengan anggukan kepala.
Nada dering Savannah yang amat kukenal bersuara nyaring. Kelap-kelip lampu display handphone menunjukkan deretan nama yang kukenal.
Azka Saputra.
Nama singkat. Hanya dua kata. Tapi cukup membuatku berhenti bernapas.
“Hallo, kenapa?” tanyaku ketus.
“Sudah dengar kabar bagus hari ini?” tanya suara berat di seberang.
“Menurutmu bagus?” balasku balik bertanya.
“Mungkin,” jawab suara itu singkat. “Dari nadanya marah, ya?”
“Mungkin,” jawabku sekenanya, mengulang ucapannya.
“Sorry, bukan maksud mau bikin khawatir. Cuma rasanya, sudah waktunya untuk semua orang tahu.”
“Tahu apa? Tahu tentang hubungan kita? Anak pemilik perusahaan yang punya hubungan dengan seorang pesuruh di perusahaan yang sama. Terus, bagusnya dari mana, Ka?” tanyaku. Lebih tepatnya meminta pertanggung jawaban dari pernyataannya barusan.
“Ya, udah. Dilihat aja besok, ya.”
“Iya, kalau memang besok aku masih bernyawa. Nggak tau juga kalau dihabisin sama Mbak-mbak senior di kantor ini.”
Suara di seberang terbahak-bahak mendengar jawabanku.
Klik! Tanpa permisi kuputuskan sepihak sambungan telepon itu. Menjengkelkan sekali. Selalu tak pernah bisa menghiburku, bahkan dalam kondisi segenting ini.
Azka memang tak berubah. Masih bangga dengan segala kecuekan yang dipunya. Tiba-tiba sebuah pesan singkat memaksaku untuk tersenyum juga akhirnya.
Mulai besok mungkin hidupmu nggak akan sama. Nggak lagi membosankan, seperti yang kamu ceritakan. Jadi, tenanglah! Percaya sama aku. -Azka-
* * *
Hariku hampir berubah. Sepertinya. Tapi, aku tak ingin mengakuinya. Aku terlalu lama tidur dalam keterbiasaanku. Kediamanku. Karena status sosialku yang memaksa untuk begitu.
Azka. Semula aku tidak berani bermimipi untuk mendapatkan hatinya. Tidak, sampai aku tahu siapa dia sebenarnya. Pertemuan singkat dengannya pun bukan sebuah kesengajaan. Terjadi begitu saja, dan masih terekam kuat di ingatanku.
Pagi itu masih terlalu pagi untuk menyapa kawanan ayam jago. Hanya jangkrik-jangkrik congkak yang memamerkan suara emasnya. Seperti pagi-pagi biasanya, aku bertugas keliling memindahkan tumpukan sampah-sampah dari tiap-tiap pintu depan rumah ke dalam gerobang kuning yang terlalu manja untuk bergerak sendiri. Selalu minta didorong olehku.
Pasukan kuning. Begitulah orang-orang menyebutku. Gajiku hanya berkisar di angka dua puluh tujuh. Tanggal dua terima, tanggal tujuh habis. Tapi, mau bagaimana lagi. Nasib orang tak ada yang boleh menolak, kan?
Pagi itu, aku baru tiba di tempat pengumpulan akhir sampah-sampah. Saat masih sibuk menurunkan sampah, seseorang menepuk pundakku dengan keras.
“Mbak, tadi lewat perumahan Morotai Blok C, kan? Udah lewat?” tanya orang itu. Ada nada panik yang kutangkap.
“Iya. Kenapa, Mas?” tanyaku, setelah menyadari sosok bayangan gelap itu menjelma menjadi sosok cowok. Rahangnya keras, dengan model rambut cepak bertegangan 240 volt.
“Bisa minta tolong, nggak? Kayaknya ada barangku yang nggak sengaja kebuang tadi.”
“Maksudnya, minta tolong…?”
“Iya, minta dicek ke dalam situ. Kali aja barangku masih bisa diselamatkan dari itu,” sahut cowok itu, sambil menunjuk ke arah gerobak sampah yang kudorong saat dia mengucapkan ‘situ’ dan ‘itu’.
“Hah…,” mataku melotot. Heran. Permintaannya benar-benar konyol.
“Tolong, deh, Mbak. Penting banget.”
“Tapi, sebanyak ini Mas….,” tanyaku memastikan pintanya.
“Aku bantuin nyari, ya,” tawar cowok itu lagi.
Tawaran yang membuatku pasrah.Aku menghela napas berat, lalu bersuara, “barangnya apa?” Tak ada cara lain lagi, selain mengikuti pintanya.
“Lempengan CD. Ada data-data penting di dalamnya.”
“Ooh…,” mulutku mengerucut, sambil terus mengobrak-abrik isi sampah mencari barang yang dimaksud.
Selang beberapa jam kemudian, aku bersuara, “ini bukan, ya?”
Cowok itu menatapku, dengan pandangan berbinar-binar. Tanpa menunggu jawabannya, aku berani bertaruh memang benda ini yang dicarinya.
“Terima kasih, ya, Mbak. Bener banget, memang ini yang kucari.”
Aku mengangguk. Dan berawal dari pertemuan singkat itulah yang membuat hidupku menjadi berubah seperti ini. Dari seorang tenaga pasukan kuning, meningkat menjadi cleaning service perusahaan.
Dari pertemuan itu, Azka merekomendasikan aku sebagai cleaning service di perusahaan milik orang tuanya. Hingga akhirnya, hubunganku dengan Azka pun menjadi dekat. Lebih dari sekedar sahabat dekat.
Awalnya aku tidak keberatan dengan perbedaan status sosial ini. Tapi semenjak kabar kemarin, membuat nyaliku menciut. Aku menarik napas panjang, sebelum memasuki gedung megah bertingkat di hadapanku. Mungkin, memang begini hidup. Menghadapi dengan penuh berbesar hati, hingga jeda bersuara.
/// Cerita pendek atau cerpen ini adalah karya terbaik dari anak-anak KF (Kampus Fiksi).