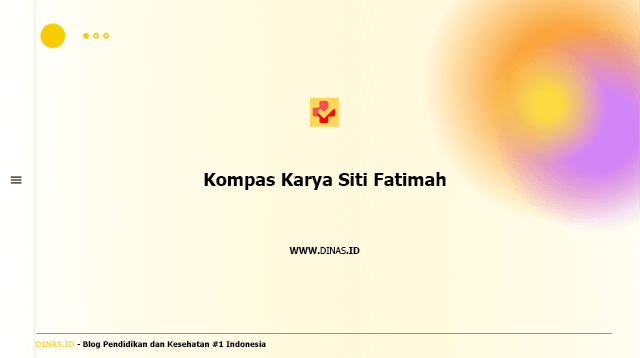Kompas
Oleh: Siti Fatimah
Pantai ini makin ramai. Tidak lagi dipenuhi suara debur pasang yang keras, mematikan. Tidak pula suara burung-burung laut yang melenguh menuju rumah. Apalagi desir angin asin yang menyejukkan. Sekarang, suara kedatangan berbagai jenis orang yang mendominasi. Berbondong-bondong mereka muncul, memenuhi tempat. Terlalu menyesakkan untukku. Karena aku benci keramaian. Jadi, kuputuskan untuk pergi menjauh. Meninggalkan teman-teman yang sibuk bermain air asin.
Sembari berjalan menyusuri pantai, tak hentinya mataku memandangi banyak hal: anak-anak yang tertawa senang karena tubuh kecil mereka terbawa ombak; para kuda yang di mataku terlihat begitu murung seolah berkata: “Kumohon, lepaskanlah kekang di leherku. Aku ingin bernafas bebas.” Di sepanjang pantai, banyak pula jejeran pedagang yang menggelar tikar seadanya atau menjinjing tas lusuh berisi barang dagangan untuk ditawarkan pada turis-turis yang sibuk memotret diri sendiri. Kebanyakan barang-barang itu adalah kerajinan tangan murah dari biota laut yang telah mati, seperti gantungan kunci atau hiasan dinding. Ada pula pedagang yang menjual barang biasa, semisal kacamata atau makanan dan minuman ringan.
Dari sekian banyak pedagang yang berseliweran di depan mata, ada satu yang menarik perhatianku. Dia seorang pria tua yang menggelar tikar lusuhnya di pojokan pantai yang sepi dan hanya sedikit orang yang lewat. Wajah yang hampir seluruhnya berkerut, kulit kecoklatannya yang kendur, bintik-bintik hitam yang menempel tanpa rima di wajahnya, serta rambutnya yang sepenuhnya putih, menegaskan usia di atas 80 tahun. Meski begitu, garis-garis ketampanan masa lampau masih terlihat satu-dua bekasnya. Pada zamannya, aku yakin banyak perawan yang mengerubunginya seperti ngengat menemukan cahaya lampu di musim penghujan.
Pria tua itu sepertinya sadar kuperhatikan. Kepalanya mendongak, menatapku sesaat, lalu tersenyum ramah. Tangan kanannya memberiku isyarat untuk mendekat. Sebenarnya, aku ingin menolak. Senja yang makin mendekat lebih menarik daripada mengobrol dengan seorang pria tua. Tapi sayang. Hatiku telah merenggut kesadaran dan kakiku pun melangkah mantap menuju si pria tua.
“Saya punya sesuatu yang sesuai untukmu,” ujarnya tanpa basa-basi saat aku telah jongkok di depannya.
Dahiku berkerut. Kuperhatikan barang-barang yang dijajakannya. Kebanyakan adalah barang-barang tua yang lebih cocok dimuseumkan atau dibuang daripada dijual. Kuambil sebuah pisau lipat yang berkarat. Sambil membolak-balik menyelidik, sebuah gagasan aneh melintas di otakku. Mungkin pisau ini pernah menusuk banyak nyawa di masa lalu dan berarti pria tua di hadapanku adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang telah insyaf.
“Pisau itu hanya pisau biasa. Dulu saya sering pakai untuk mencukur jenggot dan kumis.” Pria tua itu membuka mulut tanpa memandangku. Tangannya masih sibuk mencari sesuatu di antara tumpukan barang dalam tas ransel tuanya.
Segera kuletakkan kembali pisau itu sambil tersenyum masam. Tak lama, mataku menangkap sesuatu yang lain: sebuah tanda pangkat letnan. Seragam TNI AU juga terlipat rapi di bawahnya.
“Bapak seorang tentara?” tanyaku begitu saja.
Pria tua itu menghentikan kegiatannya. Dia menatapku sebentar dengan dahi berkerut, lalu kembali mengobrak-abrik tasnya. “Dulu saya prajurit tangguh. Sempat ikut pula saat perebutan Irian Barat. Sayang berpuluh tahun mengabdi, pangkat saya hanya sampai letnan.”
Aku mengangguk-angguk. Pikiranku menerawang kembali ke pelajaran sejarah di sekolah. Tapi seruan pria tua mengembalikanku ke pantai.
“Nah! Ini dia ketemu!” Dia tersenyum senang menatap sebuah benda di tangannya, lalu matanya teralih ke arahku. Benda itu disodorkannya padaku.
“Liontin?” ujarku bingung. Mataku bergantian menatap pria tua dan sebuah liontin lengkap dengan kalung warna keemasan yang memudar di tangannya.
“Ini bukan liontin biasa. Ini sebuah kompas.” Pria tua menjelaskan sambil membuka liontin itu.
Benar. Di dalamnya ada dua buah jarum dan singkatan-singkatan arah angin. Tapi tunggu dulu. Kenapa jarum itu tidak mengarah ke utara? Kenapa malah menunjuk ke arahku?
“Kompas ini tidak rusak. Dia memang tidak menunjuk arah utara [1]. Tapi arah yang tepat. Kompas ini memberi tahu pilihan yang terbaik untuk orang yang memilikinya. Sekarang jarumnya menunjuk arahmu karena saya ingin mewariskan kompas ini pada orang yang tepat. Dan benar. Ternyata itu kau.”
Kerutan di dahiku makin dalam. Penjelasannya tidak menghilangkan kebingungan, malah menimbulkan lebih banyak tanda tanya di kepalaku.
“Kau tahu? Dulu kompas ini pernah memberi tahu saya sesuatu. Tentang pilihan yang penting.” Dia kembali menjelaskan tapi matanya menerawang. Menerobos mesin waktu. “Dulu saya bimbang antara menikah atau masuk militer. Saya pun membuka kompas ini. Jarumnya ternyata menunjuk arah kekasih saya saat itu yang menangis sedan di samping saya.
“Tapi saya terlalu pongah untuk menuruti kemauan Sekar. Jiwa muda saya terlalu bergelora. Dan saya pun memilih militer. Tapi seperti yang sudah saya bilang, karier saya di militer tidak mulus. Kekasih saya pun terlanjur pergi dan menikah dengan pria jodohan keluarganya.
“Sejak itu saya berpikir seharusnya saat itu menuruti saja arah kompas itu. Bukannya lari dan pergi.”
Mataku tak berkedip menatapnya. Bukan karena mendengar kisah cinta tragisnya tapi karena tersadar bahwa dia telah membaca pikiranku hingga dua kali!
“Saya tidak bisa membaca pikiran,” ujarnya setelah kembali dari “perjalanan waktunya”. Dia terkekeh geli. Memperlihatkan gusi tanpa gigi yang dimilikinya.
Aku menelan ludah. Sekarang, aku benar yakin seharusnya tadi lebih memilih senja daripada mengobrol dengan pria tua ini.
“Ambillah. Ini untukmu. Kau tidak usah bayar. Karena saya tidak punya anak atau cucu atau mungkin keluarga lain yang masih hidup, kompas ini saya wariskan padamu.”
Ragu menyelimutiku kini. Antara percaya dan tidak dengan kemampuan “ajaib” kompas ini. Lagipula aku tidak sedang dalam kondisi butuh petunjuk dari sebuah kompas.
“Kau tidak harus menggunakannya sekarang. Kelak saat kau penasaran akan sesuatu atau dihadapkan pada pikiran-pikiran yang membingungkan, dia akan menunjuk ke arah yang tepat.”
****
“Doni! Kamu denger nggak aku bilang apa?!” Fitri menegurku lagi. “Berhentilah melamun! Tugas ini harus segera selesai. Besok udah harus dikumpulin,” lanjutnya sambil menyeringai sebal.
Aku hanya bisa nyengir sambil minta maaf. Segera kembali kuarahkan mata ke laptop. Bukan untuk membaca datanya. Apalagi mengerjakan tugas bagianku. Aku hanya ingin menghilang dari tatapan kesalnya.
Belakangan memang dia dan teman-temanku yang lain sering menegur dan mengomeliku karena terlalu sering melamun. Entah itu di kelas atau saat tengah hang out. Aku sendiri tidak tahu benar mengapa melamun. Tiba-tiba saja lamunan itu menyergapku. Dan selalu saja berisi hal sama. Tentang kerinduan dan seorang gadis bernama Cantik.
Setelah kerja kelompok itu selesai dan Fitri pergi meninggalkanku sebentar untuk beli siomay dan air mineral dingin di kantin, kukeluarkan kompas yang dulu kudapat dari seorang pria tua saat berdarmawisata dua tahun lalu. Sejak kumiliki, kompas itu hanya tersimpan rapi dalam almari. Baru-baru ini saja kubawa di tas dan baru sekarang kuperhatikan betul-betul.
Kubuka kompas itu. Jarumnya berputar cepat, tak tentu arah. Ia terlihat seperti tengah mencari sesuatu.
“Cantik,” sebutku lamat. Khidmat. Jarum itu pun seketika berhenti berputar dan menunjuk ke satu arah. Di arah yang sama, seorang gadis berdiri menghadapku. Mata kami pun saling bertemu. Membungkamku dalam beku.
“Kompas ini juga akan menunjukkan siapa jodoh yang kau lamunkan berkali-kali,” ujar pria tua dulu padaku.
Surabaya, Februari 2014
[1] Dalam film Pirates of The Caribbean, kapten Jack Sparrow memiliki kompas yang tidak menunjuk arah utara tapi arah yang menunjuk pada letak sesuatu yang sedang dicari dan diinginkan oleh pemegang kompas.
/// Cerita pendek atau cerpen ini adalah karya terbaik dari anak-anak KF (Kampus Fiksi).