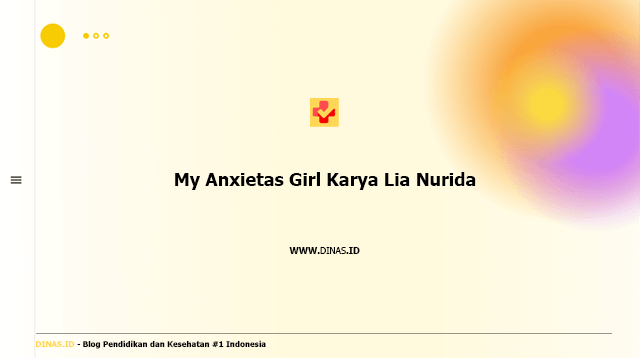My Anxietas Girl
Oleh: Lia Nurida
(Kecemasan eksistensial yang dialami oleh si tokoh, seperti kecemasan akan masa depan, cemas kematian, dll, lalu bagaimana si tokoh melampauinya)
Pukul dua kurang lima belas menit, dini hari.
Anez terbangun dan mendapati tubuhnya basah oleh keringatnya sendiri. Matanya yang bulat bergerak-gerak cepat. Ia tengah berusaha keras agar bisa menguasai diri..
Aku benci seperti ini…!! teriak gadis itu dalam hati.
Seolah telah hapal dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, Anes segera mencengkeram erat t-shirt putih longgar yang ia kenakan. Ia kemudian memegangi dadanya yang seolah mulai menciut dengan sendirinya. Ia sesak napas. Susah payah ia menghirup udara yang kesulitan masuk memenuhi rongga paru-parunya.
Ini mimpi. Pasti mimpi! bisiknya pada diri sendiri.
Bukan pertama kalinya ia merasakan hal seperti ini. Terbangun dini hari dalam keadaan jantung berdebar dan seluruh tubuh yang kuyup oleh keringat.
Anes segera berjingkat dari kasur dan terseok berjalan menuju meja kerja yang berada tak jauh dari tempat tidurnya. Dalam gelap Anes berusaha menyesuaikan pandangannya.
Selalu seperti ini. Gadis itu membenci dirinya sendiri jika mulai mengalami hal seperti ini hanya karena ia mencemaskan sesuatu. Semua ini berawal dari kejadian siang tadi.
“Nes, itu mobilnya Adrin kan?” celetuk Dina. Sahabatnya itu mengangkat telunjuknya ke seberang trotoar dari tempatnya berdiri.
Lancer putih dengan plat B 7689 KLJ, deretan kombinasi angka dan huruf yang sudah sangat ia hapal di luar kepala baru saja berhenti di depan sebuah kafe dengan papan nama bertuliskan Espressiola
Anes segera menghentikan langkahnya dan melemparkan pandangan ke arah yang ditunjuk Dina. Perhatiannya terpusat pada mobil yang ia kenal betul siapa pemiliknya itu.
“Adrin sama siapa?”
Pertanyaan dari Dina langsung terjawab ketika seorang pria muda dengan setelan kemeja biru laut keluar dari salah satu pintu kemudian berjalan memutar dan membukakan pintu yang satu lagi. Seorang gadis dengan perawakan tinggi langsing yang mengenakan setelan blazer dan rok potongan A selutut muncul dari sana. Mereka berdua kemudian berjalan beriringan menuju café.
Senyum lebar keduanya serta percakapan kecil berujung tawa yang tak bisa terdengar oleh Anes dari seberang keduanya membuat jantung Anes berdetak kencang saat itu juga.
Kesadaran Anes kembali. Ia menggelengkan kepala kencang-kencang untuk menghilangkan bayangan tadi siang. Tangannya yang gemetar berusaha keras membuka laci-laci meja.
Setelah berhasil menemukan botol yang ia cari, ia segera mengeluarkan isinya. Satu butir, ia merasa tidak akan cukup. Dua, atau mungkin tiga butir. Ya, dengan sekali teguk akhirnya ia menelan tiga butir xanax yang selama setahun belakangan ini telah menjadi sahabat dekatnya jika ia mengalami serangan seperti ini.
Dengan napas yang sudah mulai teratur ia duduk di tepi ranjangnya. Ditatapnya cincin yang melingkar di jari kanannya. Dengan keyakinan yang sebenarnya tak sepenuhnya ia yakini, ia mencabut cincin itu dari sana kemudian kencang-kencang ia lempar ke ujung ruangan.
Yang ia tahu. Ia harus mengakhiri semua ini.
***
Tidak biasanya Anes mengajaknya makan siang bersama. Adrin sangat tahu, tunangannya itu adalah gadis yang tidak terbiasa makan siang di luar. Anes lebih senang berdiam diri di studionya, berkutat dengan cat dan kanvas. Apalagi minggu depan ia akan menggelar pameran tunggal perdananya.
Namun ketika pagi tadi ia menerima telepon dari Anes, ia tahu bahwa suara Anes menyiratkan bahwa gadis itu mengajaknya bertemu untuk membicarakan sesuatu yang serius.
Lima belas menit berlalu. Ia masih menunggu kedatangan Anes. Gadis itu belum juga muncul. Ketika pesanan espressonya sudah siap pun belum ada tanda-tanda gadis yang sudah bersamanya selama dua tahun itu datang.
Baru saja Adrin hendak menelepon kekasihnya itu, suara gemerincing lonceng yang tergantung di atas pintu café membuat Adrin berpaling dari ponselnya.
“Anes,” gumamnya.
Ia memasang senyum lebar melihat gadis itu menuju ke arahnya. Namun ia segera mengernyit ketika tahu bahwa Anes terlihat jauh lebih pucat. Adrin bahkan menangkap warna kecokelatan di bawah mata Anes.
“Kamu sakit?” sambut Adrin. Pria itu berdiri hendak memeluk Anes. Namun gadis itu menghindar dan memilih untuk langsung duduk.
“Aku pesenin cappuccino ya,” tanyanya.
“Nggak usah,” potong Anes cepat.
Adrin terkesiap. Ia menangkap nada tidak menyenangkan dalam kalimat Anes baru saja.
“Aku enggak akan lama.”
Adrin mengangguk dan kembali duduk.
“Drin, sebaiknya kita batalkan saja pernikahan kita.”
***
Adrin tergopoh-gopoh menuju ruang ICU. Baru beberapa jam lalu ia mendapatkan kabar bahwa Anes masuk rumah sakit. Gadis itu ditemukan tak sadar diri di kamarnya karena overdosis obat. Begitu menurut kabar yang ia terima.
Yang ada dalam benak Adrin adalah apa yang sebenarnya terjadi pada gadisnya itu. Obat apa yang diminumnya hingga overdosis.
Sesampainya di kamar ICU rupanya Anes belum sadarkan diri. Pundak Adrin ditepuk dari belakang oleh seorang wanita paruh baya yang sudah ia kenal betul. Mama Anes.
“Anxietas?!” pekik Adrin.
Ibu Anes mengangguk. “Sudah setahun belakangan ini,” tambahnya.
“Kenapa ia tidak pernah bilang sama saya?”
Mama Anes hanya mengendikkan bahu.
***
Adrin melihat dari jauh mantan kekasihnya yang tengah berdiri di depan deretan lukisan-lukisan karyanya. Gadis itu terlihat jauh lebih segar dari sebelumnya.
Beberapa hari setelah Anes pulang dari rumah sakit mereka sempat bertemu. Tetapi tidak banyak yang mereka bicarakan. Anes tetap dengan pendiriannya.
“Kamu pasti deg-degan!”
Anes menoleh ke asal suara. Gadis itu tampak tercengang dengan kehadirang Adrin.
“’Dari mana kamu tahu aku disini?”
Adrin tersenyum tanpa menjawab apa pun. Ia kemudian berdiri di sebelah gadis yang hingga saat ini masih sangat dcintainya itu.
“Dari dulu aku selalu mengagumi karyamu, Nes”
Anes mengernyit. Kemudian ia memutar badan dan menghadap kea rah lelaki yang beberapa minggu lalu ia putuskan begitu saja dengan alasan yang ia sendiri tak tahu akibatnya.
“Kamu mau ngapain sebenarnya?”
“Nes, aku tahu soal penyakitmu”
Anes menghela napas panjang. Ia tidak berani berkomentar.
“Nes, aku tahu tidak mudah menghadapi penyakiymu. Ketakutan yang tidak bisa kau kendalikan sendiri itu.”
Anes masih terdiam. Ia merasakan jemari Adrin mulai memenuhi celah jarinya. Ia berdebar meski tak sanggup menolaknya.
“Nes, ijinkan aku menemanimu melewatkan penyakit itu,” kata Adrin lembut.
Anes memutar kepalanya. Tatapan teduh Adrin mengubah pendiriannya.
***
/// Cerita pendek atau cerpen ini adalah karya terbaik dari anak-anak KF (Kampus Fiksi).