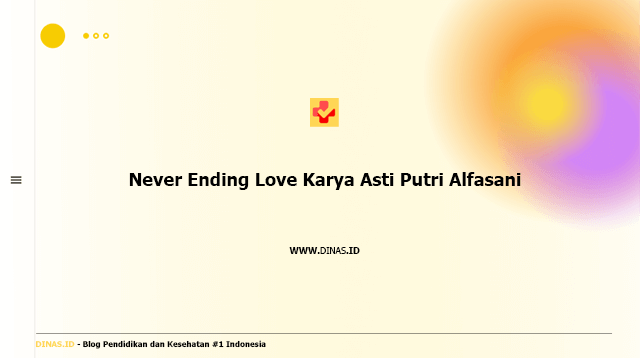Never Ending Love
oleh: Asti Putri Alfasani
Sepertinya Tuhan baru saja menekan tombol mute. Semua terasa bergerak lamban tanpa suara. Rintik gerimis di luar sana, orang-orang yang berlalu lalang, gurauan, tawa, bahkan ruangan ini seketika terasa aneh dan berputar-putar. Perlahan-lahan aku merasa ada yang naik sampai ke tenggorokan dan membuat dadaku sesak. Rasanya seperti air mata.
Dia datang. Masih dengan pesona yang sama, setidaknya di mataku. Berjas abu-abu tua dan dasi kotak-kotak warna biru, dia tampak jauh lebih berkharisma dari yang sering kulihat di televisi.
Langkahnya tegap dan sepertinya dia akan menuju ke… arahku! Mendadak kurasakan lututku lemas.
Dilemparkannya seulas senyum. Senyum yang sejuta kali lebih memabukkan dari senyumnya di layar kaca. Kerja otakku tersendat seketika. Aku tak tahu harus bicara apa jika dia benar-benar menghampiriku. Aku hanya berharap semoga hatiku cukup kuat untuk menyapa satu dari sekian serpihan kecil masa lalu ini.
Tolong aku, Tuhan…
Tapi baru beberapa langkah dia berjalan, segerombol wartawan menghadang. Ia berhenti dan menanggapi dengan ramah satu persatu pertanyaan yang mereka ajukan. Aku tetap berdiri, terpaku dengan deru jantung yang makin tidak menentu.
Dia yang dulu kucinta, sekarang bukanlah seseorang yang bisa dipandang sebelah mata.
***
Suatu Minggu pagi di taman kota, enam tahun yang lalu… Tentang sebuah pengorbanan…
Kuketuk-ketukkan jari ke bangku. Sudah hampir sepuluh menit berlalu dengan kaku tanpa ada percakapan apa pun. Aku mulai bosan. Adrian masih diam saja, membolak-balik setumpuk kertas. Makin kupandang, air wajahnya tampak makin keruh.
“Naskah ini kemarin batal disiarkan,” ujarnya lirih. Fiuh, akhirnya dia buka mulut juga.
Kutatap wajahnya sambil bertanya, “Kenapa?”.
Bukannya menjawab, ia malah menyodorkan naskahnya. “Coba kamu baca sebentar.”
Aku menerima tapi tidak tahu harus berkata apa. “Kenapa batal disiarkan?”
“Aku juga nggak tahu.” Ia mengedikkan bahu. “Menurut Pak Deni sih kurang faktual. Gila kali ya, padahal aku semalaman nggak pulang, begadang di TKP supaya dapet info yang bener. Eh, ujung-ujungnya batal disiarin. Kalau tahu gitu, mending aku tidur aja di rumah.”
Hening sejenak.
“Pak Deni emang nggak suka sama aku,” lanjutnya. “Apa-apa yang aku lakuin selalu aja salah.”
Adrian mengusap wajahnya, frustrasi. Matanya terlihat lelah.
Kukembalikan naskah yang kupegang. Diam-diam aku berpikir keras, mencoba menggeledah berkas kata-kata di tempurung kepala yang sekiranya tepat kuutarakan untuk menghiburnya. “Ya sudah, jangan dipikir lagi. Sekarang, gimana kalau kita makan es buah di depan itu? Biar rileks, yuk…” Sialan, kalimat macam apa ini?
Adrian memandangku sambil melengkungkan sebuah senyum. Tampak terpaksa, memang. Tapi kan…
Drrrrttt… dddrrrrrttt…
Ponselnya bergetar… lagi? Kencanku diganggu telepon kantornya lagi?
“Ya, Pak Deni?”
Sudah kuduga. Telepon dari kantornya. Lagi dan lagi! Spontan kuhela napas kesal sambil memejamkan mata. Selama bersamanya satu tahun ini, aku sudah tahu bahwa seorang jurnalis memang tak punya hari Minggu. Tapi hal seperti ini hampir selalu terjadi!
“Sekarang, Pak?” lanjutnya. “Oke, saya ke sana.”
Aku duduk lagi, menunggunya selesai bicara.
Ia berbalik menghadapku. “Pak manajer nelepon, katanya ada demo di depan SMA Pertiwi. Aku mau ke sana sekarang. Maaf ya, Vin. Nanti kamu pulang sendiri nggak apa-apa kan?” jelasnya tergesa-gesa, sibuk merapikan berkas-berkas yang tadi ia keluarkan.
“Oke, sekali lagi maaf banget ya… Aku berangkat dulu, love you. Bye…” pamitnya sambil memakai ID card pers yang ternyata sudah disimpannya di balik kemeja. Tanpa menunggu jawabanku, dia sudah menghilang bersama motor matic hitamnya di gerbang taman. Ugh! Ide makan es buah yang tadi kuusulkan tiba-tiba manjadi memuakkan!
Meskipun begitu, sambil melangkahkan kaki ke arah berlawanan, mataku sempat memejam sejenak dan seuntai doa meluncur begitu saja, “Tuhan, lindungi dia…”
***
5 Januari di lobi kantornya, lima tahun yang lalu… Tentang sebuah kesetiaan…
“Adrian belum datang, Vin…” seorang wanita cantik yang duduk di seberang meja berkata kepadaku sambil tersenyum.
Kubalas senyumnya, setengah takjub karena resepsionis cantik ini tahu alasan kedatanganku kemari bahkan ketika aku belum berbicara apa-apa. Ya, ya, wanita ini memang sudah hapal.
“Belum pulang?” ulangku. “Jam segini belum pulang?”
Wanita itu tertawa. “Jangan khawatir. Dia bisa menjaga diri,” katanya.
“Eh, ya, tapi seharusnya kan sudah pulang…” aku bergumam sambil melongok ke pintu kaca. Tampak matahari nyaris tenggelam ditelan malam.
Wanita di seberang meja itu kembali mengalihkan perhatiannya ke layar komputer. “Ada perlu apa, Vin? Sebenarnya jam dua tadi dia sudah selesai bertugas di luar dan kembali kesini menyelesaikan naskah hasilnya meliput seharian. Tapi satu jam yang lalu dia pergi lagi. Sepertinya buru-buru. Mungkin ada kejadian baru lagi dan harus segera diliput.” Ia berceloteh panjang lebar tanpa memandangku. “Mau menunggu atau…?”
Aku mengangguk yakin. “Ya sudah, aku tunggu di teras depan saja…” jawabku.
Kuhempaskan tubuh di sebuah bangku panjang sambil sesekali melihat jam tangan. Sudah tidak terhitung lagi ada berapa orang yang lalu lalang, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, sampai seorang pria gemuk botak berwajah sengak: Pak Deni si manajer.
Berulang kali pula kulirik kotak karton berukuran sedang yang tergolek di samping kananku. Aku mendesah. Berani sumpah, kue tart di dalamnya pasti sudah bosan menunggu, seperti ibuku di rumah yang pasti juga sudah geram menanti kepulanganku. Bodo amat!
Aku sudah bertekad akan menunggu sampai dia datang. Kupikir tidak lucu kalau aku membawa kue ini pulang, padahal hari esok sudah menjelang. Hari ulang tahunnya ya sekarang, bukan besok apalagi dua hari mendatang!
Tepat ketika waktu hampir melunturkan tekadku, Adrian dengan motor hitamnya memasuki pintu gerbang.
“Lho? Vina?” Ia berjalan tergopoh-gopoh begitu melihatku. “Ngapain kamu di sini? Sudah malam. Ayo kuantar pulang! Nanti ibumu marah-marah. Nanti kamu sakit! Ngapain ke sini segala? Tuh, kedinginan kan?” ucapnya bertubi-tubi sambil melepas jaket cokelat kesayangannya, menyisakan tanda pengenal pers di luar kemeja berwarna biru muda.
Aku tertawa geli sambil menggodanya, “Jadi, kalau lagi wawancara sama narasumber kamu juga maksa begitu ya?”
Adrian berkacak pinggang di depanku. “Oke, anggap aja itu lucu. Sekarang aku antar kamu pulang,” katanya sambil menggelengkan kepalanya beberapa kali. “Sudah jam tujuh,” tambahnya lagi.
Lalu aku berdiri dari bangku, meraih kotak karton dan membukanya tepat di depan raut lelahnya. “Happy birthday!”
Ia tertegun sejenak dan aku tertawa. Dalam keadaan seperti itu, wajahnya tampak begitu lucu. Ya, lucu! Aku suka sekali wajah kotornya, wajah hasil jilatan mentari yang disempurnakan oleh peluh yang berleleran. Dan satu lagi. Di balik kacamata minusnya, sepasang mata yang bersorot tajam senantiasa menebar aura intelegensia. Keren sekali!
“Terima kasih…” ucapnya lirih.
***
Suatu senja, lima tahun yang lalu… Tentang sebuah pertentangan…
Kunikmati setiap hentak langkah sepatuku yang beradu dengan aspal jalanan. Dari kampus sampai rumah, rasa kesalku sudah berangsur-angsur berkurang.
“Aku pulang…” teriakku sambil membuka pintu.
Ibu tergopoh-gopoh menyambutku. “Lho, tadi kamu bilang pulangnya dijemput Adrian? Kok sekarang jalan kaki?”
Aku menggerutu pelan. “Nggak tahu juga, Bu. Sudah setengah jam Vina nunggu, tapi Kak Adrian-nya nggak datang-datang.” Aku meneguk ludah karena sebersit rasa bersalah menyergapku begitu aku melafalkan kebohongan itu pada Ibu. Sebenarnya, tadi sudah satu jam aku menunggu.
Aku melanjutkan, “Akhirnya Vina naik angkot terus jalan kaki dari depan gang sana.” Kulengkungkan seulas senyum terpaksa.
Di luar dugaan, ibuku mencibir lalu berujar dengan nada tidak suka, “Dari awal, Ibu nggak suka kamu dekat sama dia, Vina… Kerjaan wartawan itu risikonya besar lho.”
Tanpa sadar aku terhenyak. Dalam pembicaraan apa pun tentang Adrian, status jurnalisnya selalu menyulut permasalahkan.
…
Keesokan harinya, aku baru akan menyendokkan nasi ke piring ketika Ibu dan Ayah memandangku lekat-lekat.
“Vina, Ibu sama Ayah mau bicara.”
Aku mendongak, menatap mata Ibu yang sepertinya akan menuntut sesuatu. Dadaku terasa sesak dan aku mulai menduga-duga…
“Semalam ada yang mencarimu.” Ayah berkata dengan suara berat. “Teman Adrian,” lanjutnya.
Nasi yang kutelan mendadak terhenti di tenggorokan. Ada apa?
“Adrian sekarang di rumah sakit. Nanti sore kamu boleh kesana, menemuinya untuk yang terakhir.” Ayah berkata dengan nada memaksa, dengan penekanan penuh di bagian terakhir. Ya, TERAKHIR. “Dan satu lagi,” lanjutnya, “Ayah tidak menerima bantahan apa-apa.”
***
From : mr_adrian@yahoo.com
To : [email protected]
Dear Vina,
Terima kasih sudah menjenguk dan menyejukkan sakitku meskipun hanya sebentar. Sebenarnya aku tidak apa-apa. Ya, kamu sendiri tahu, aku hampir selalu ada dalam bahaya setiap saat karena itu memang hidupku.
Well, aku ingin bercerita sedikit tentang apa yang terjadi kemarin. Seharusnya aku bercerita padamu saat kamu datang ke rumah sakit tadi siang. Tapi aku tidak jadi melakukannya karena suaraku mendadak lenyap saat kamu tiba-tiba berkata bahwa kita tidak bisa bersama lagi. Kamu tahu, rasanya seperti… entahlah, aku tidak tahu bagaimana menuliskannya.
Jadi ceritanya, Vin, aku sedang ditugaskan meliput demonstrasi di depan kantor walikota. Semakin sore situasi semakin ricuh, tidak terkendali, dan ya, aku terjebak disana… aku tidak perlu menceritakan apa yang terjadi kepadaku, tapi seperti yang kamu lihat tadi, keadaanku tidak baik. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ini hanya luka-luka kecil yang akan sembuh sebentar lagi.
Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa luka-luka kecil ini membuat orangtuamu melarang kita untuk bersama. Aku bisa memahami perasaan mereka, Vin. Tentunya mereka tidak ingin kamu dekat dengan orang yang hidup dalam risiko seperti aku. Dan satu lagi, mau tidak mau, kamu harus percaya bahwa restu orang tua adalah segala-galanya.
Oh iya, bukan kamu saja yang terluka. Aku juga. Dan jangan sedih, karena meskipun kita tidak bersama, bukan berarti sudah tidak ada cinta.
P.S. Jangan mengirim sms. Aku perlu berusaha keras untuk mulai menjauh.
Aku merenung menghadap layar komputer. Oke, mungkin ini memang yang terbaik untuk kami. Tanpa kusadari, pipiku mulai terasa hangat oleh sungai-sungai kecil.
***
Hari lainnya…
From : mr_adrian@yahoo.com
To : [email protected]
Dear Vina,
Apa kabar? Aku rindu padamu, kamu tahu? Aku mulai nyaman di Jakarta, Vin. Sedikit demi sedikit karirku naik. Andai kamu di sini, kamu pasti senang melihatnya… Apa yang dulu sering kita angankan bersama sekarang benar-benar terjadi, Vin. Khayalanmu dulu tentang aku yang muncul di televisi sebagai pembaca berita sekarang benar-benar aku alami. Aku dapat banyak pengalaman baru. Wawancara dengan pejabat-pejabat penting negara, politikus terkenal, dan buaanyaaak lagi. Kamu sudah pernah melihat penampilanku di televisi kan? Menurutmu bagaimana? J
Vin, terima kasih sudah menemaniku di masa-masa yang sulit. Aku masih ingat bagaimana kamu menungguku. Aku masih ingat bagaimana wajahmu yang kecewa saat aku mendapat tugas liputan mendadak dan tidak bisa menjemputmu. Aku masih ingat bagaimana kamu selalu ada untuk menemaniku saat aku kesal karena dimarahi Pak Deni. Aku masih ingat semuanya.
Satu hal yang kusesali, kenapa justru kita tidak bersama saat aku sudah meraih yang jauh lebih baik sekarang? Dan kenapa yang kita inginkan tidak selalu bisa kita dapatkan? Tapi, sudahlah. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu:
I still love you…
P.S. : Jangan dibalas. Aku tidak sanggup menyiksa diriku sendiri.
***
Suara pembawa acara menyadarkanku dari angan-angan masa lalu. Ruangan semakin ramai. Sepertinya acara peresmian gedung baru stasiun televisi ini sudah akan dimulai.
“Hai, Vina. Apa kabar?” Aku terhenyak mendapati Adrian sudah berdiri di hadapanku.
Kutelan ludah dengan susah payah sebelum menjawab, “Mmm, ya, h-hai. Aku… baik. Kamu?”
Sungguh, lututku lemas. I still love you…
Aku ingin mengatakannya, tapi tidak bisa.
Adrian tersenyum. Di balik kacamatanya, kulihat matanya juga tersenyum. Lututku semakin lemas.
“Selamat ya, novelmu jadi best seller. Kamu hebat...” katanya.
“Eh, oh, ya, terima kasih…” jawabku. Dulu kau yang mengajariku menulis…
Aku ingin mengatakannya tapi sekali lagi kata-kata itu hanya sebatas bergema di telingaku sendiri.
“Kamu juga hebat, sekarang sudah jadi produser televisi nasional…” pujiku. Fiuh, akhirnya aku bisa juga bicara dengan lancar.
“Tahun-tahun berlalu begitu saja ya. Tahun-tahun yang…” ia berhenti sejenak lalu melanjtkan lirih, “…menyiksa.”
Kuhela napas panjang untuk membendung butir bening di sudut mata. “Ya. Aku senang sekarang kita bertemu lagi,” imbuhku lirih. Perih.
Tiba-tiba seorang gadis cantik mendekat. “Sayang, kok aku nggak dikenalin sih?” katanya pada Adrian.
Adrian memandangku lalu menoleh pada gadis itu. “Kenalin, ini Sevina Aryani.”
Gadis itu terbelalak sejenak. Ia memandangku. “Wah, Anda penulis novel itu ya? Jadi kalian saling kenal? Perkenalkan, aku Sinta, tunangannya Ian…” katanya antusias.
Kuulaskan senyum manis yang ternyata malah mengiris hatiku sendiri. “Hai, Sinta…” sapaku. Dia bilang apa tadi? Tunangan?
Lalu gadis itu menoleh pada Adrian dan menggelayut di lengannya dengan manja. “Oh iya, Sayang, gimana kalau kita undang aja Mbak Sevina ini ke pesta pernikahan kita? Adikku ngefans banget sama Mbak Sevina ini lho,” ujarnya.
Apa katanya? Menikah?
Adrian mengangguk, tampaknya sedikit ragu. “Mmm, ya, b-boleh…” jawabnya lirih.
“Datang ya, Mbak, undangannya menyusul.” Sinta menjabat tanganku erat sambil tersenyum lebar. “Eh, Sayang, kamu dicari Pak Direktur tuh! Yuk, kesana! Kan kamu harus siap-siap untuk ngasih sambutan,” katanya pada Adrian.
Adrian mengikuti Sinta menuju ke samping panggung. Tapi baru dua langkah berjalan, tiba-tiba ia menoleh lagi ke arahku setelah berbisik sejenak pada Sinta. Gadis itu pun berjalan sendirian.
“Terima kasih, Vin, untuk cintamu, dulu. I still love you…” bisiknya pelan.
Jantungku serasa lepas dari tempatnya. Tanpa sadar aku membalas bisikannya dengan kalimat yang di telingaku sendiri terasa luar biasa menyakitkan, “I love you too…”
Seketika aku membekap mulut. Apa yang baru saja kukatakan? Kuharap tidak ada yang mendengar.
Tiba-tiba sebuah tangan mungil terasa menarik gaunku dari belakang. “Bunda, Feri mau pipis. Anterin Feri ke kamar mandi ya, Ayah masih ngobrol sama Om Yahya.”
Aku menoleh dan kudapati Feri, putraku yang sedang lucu-lucunya ini, sedang menatapku manja sambil menunjuk sudut kanan panggung. Di sana tampak suamiku sedang berbincang ringan dengan kolega-koleganya. Buru-buru kugamit pergelangan tangan Feri untuk segera pergi tapi Adrian malah melangkah mendekat.
“Hai, jagoan!”
“Om ini siapa, Bunda?”
“Eh, ini… Ini… Om Ian.”
Mendadak Adrian berjongkok menyamai tinggi Feri lalu berbicara pelan dengan nada tertahan, “Hai, Feri. Jangan panggil Om ya… Soalnya saya ini ayah kamu.”
“ADRIAN, DIAM!”
~end~
/// Cerita pendek atau cerpen ini adalah karya terbaik dari anak-anak KF (Kampus Fiksi).